Resensator: Bdikar Anumtiko Ling Kricas
Buku Malin Deman: Dalam Pusaran Konflik Agraria karya Erwin Basrin mengangkat secara mendalam kisah nyata perjuangan masyarakat adat Malin Deman di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, dalam menghadapi konflik agraria akibat ekspansi perusahaan sawit PT Daria Dharma Pratama. Narasi dibangun dari pengalaman langsung penulis dalam mendampingi komunitas, menunjukkan bagaimana masyarakat yang selama puluhan tahun menggarap tanahnya secara turun-temurun tiba-tiba dikriminalisasi, dituding sebagai perambah, dan bahkan ditangkap. Konflik ini menjadi cermin betapa hukum dan kebijakan negara sering kali tidak berpihak pada realitas sosial masyarakat adat, melainkan pada kekuatan kapital yang difasilitasi oleh negara melalui izin Hak Guna Usaha (HGU).
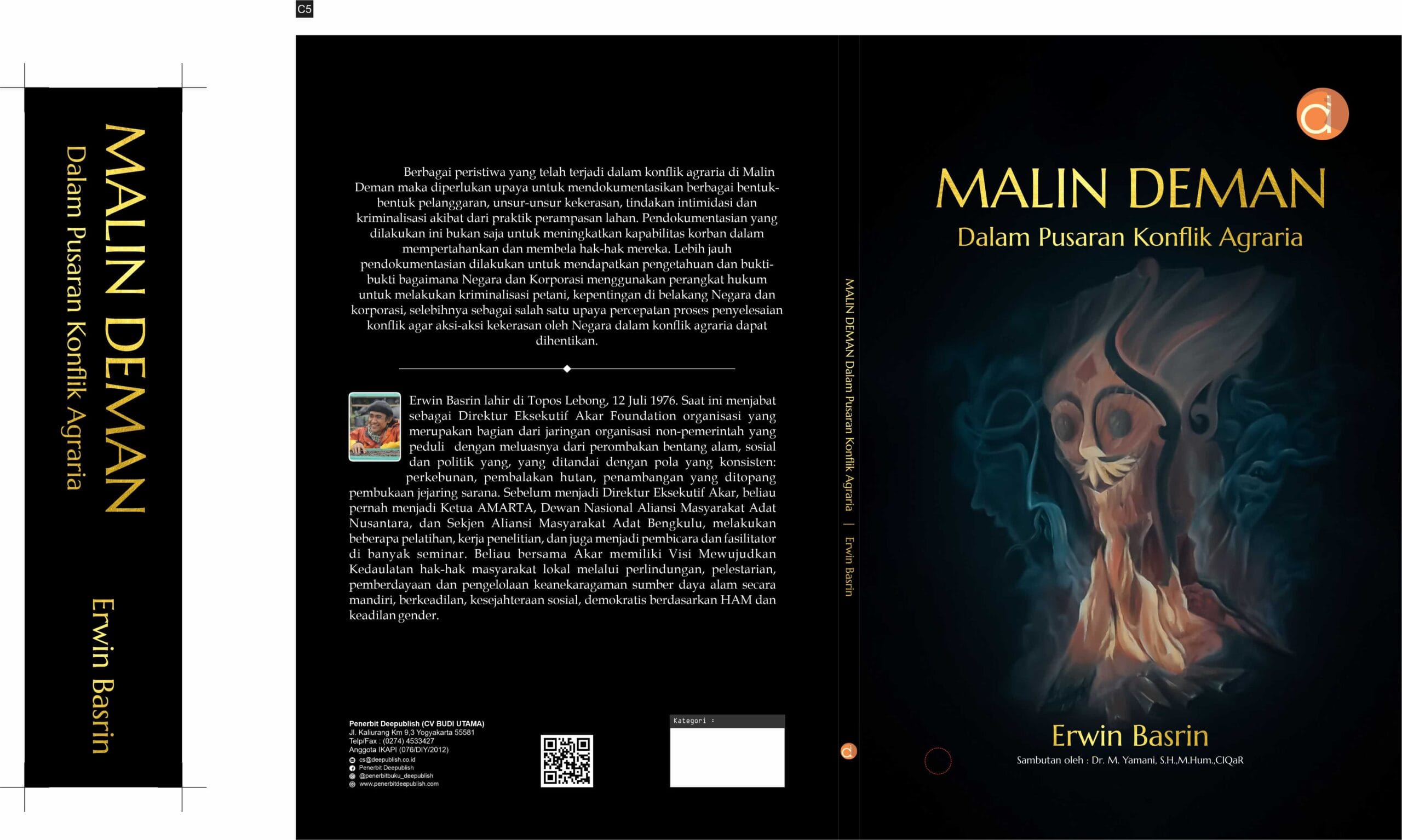
Dalam buku ini, Erwin Basrin tidak hanya mengungkap fakta-fakta konflik, tetapi juga menggambarkan strategi perlawanan masyarakat adat yang tetap bertahan dan melawan dengan berbagai cara: mulai dari aksi duduk di lahan, pemetaan partisipatif, hingga pengajuan gugatan hukum. Di balik cerita konflik, terdapat semangat komunitas untuk mempertahankan hak atas tanah sebagai ruang hidup, bukan sekadar aset ekonomi. Tanah dalam pandangan masyarakat Malin Deman bukan benda mati, melainkan warisan leluhur yang menyatu dengan kehidupan, identitas, dan martabat mereka. Karena itu, perjuangan agraria bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal keberlanjutan budaya dan hak kolektif.
Buku ini penting dibaca oleh siapa pun yang ingin memahami bagaimana hukum agraria di Indonesia masih penuh paradoks: di satu sisi menjanjikan perlindungan terhadap hak ulayat dan fungsi sosial tanah, namun di sisi lain justru memfasilitasi penguasaan oleh korporasi besar melalui legalisasi formal. Malin Deman menunjukkan bahwa konflik agraria bukan sekadar konflik lahan, melainkan pertarungan narasi antara cara negara memandang tanah sebagai objek administrasi dan bagaimana masyarakat adat memaknainya sebagai sumber kehidupan. Ini adalah catatan sejarah yang sekaligus ajakan untuk membangun hukum yang adil, hidup, dan berpihak pada mereka yang selama ini disingkirkan dari peta pembangunan.
Buku ini mengisahkan bagaimana wilayah adat Malin Deman dirampas oleh PT Daria Dharma Pratama (PT DDP), sebuah perusahaan sawit yang memperoleh izin Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan yang secara turun-temurun digarap masyarakat. Sejak awal, tidak ada konsultasi atau persetujuan dari masyarakat adat. “Mereka datang dengan buldoser dan surat izin dari atas, bukan dengan dialog dan kesepakatan,” tulis Erwin Basrin dalam pengantar buku ini.[1]
Konflik tersebut bukan hanya tentang tumpang tindih klaim hukum, tetapi juga ketimpangan kekuasaan antara negara, perusahaan, dan warga desa. Negara, melalui aparatus hukum formal, lebih banyak hadir sebagai fasilitator korporasi daripada pelindung hak rakyat. Dalam satu bagian, Erwin Basrin mencatat: “Kriminalisasi terhadap petani bukan karena mereka melakukan kejahatan, melainkan karena mereka menolak dilenyapkan dari sejarah penguasaan tanah mereka sendiri.”[2]
Yang menarik, buku ini tidak berhenti pada pengungkapan tragedi. Ia juga memuat perlawanan-perlawanan kecil namun konsisten: pengorganisasian masyarakat, pemetaan partisipatif, gugatan hukum, dan advokasi kebijakan. Erwin Basrin menulis: “Keadilan tidak datang dari negara, ia diperjuangkan dari bawah dengan rasa sabar dan keberanian.”[3]
Buku ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana struktur hukum formal sering kali gagal memahami struktur sosial adat. Dalam konteks UUPA 1960 yang sebenarnya memberi ruang pada hak ulayat, praktiknya justru kerap bertentangan. Hukum menjadi alat kekuasaan, bukan keadilan. Inilah yang disebut Boaventura de Sousa Santos sebagai “hukum mapan versus hukum hidup”[4] pertarungan antara norma tertulis dan praktik yang dijalankan dalam komunitas.
Kelebihan utama buku ini adalah keberaniannya menempatkan konflik agraria bukan sekadar masalah pertanahan, tapi sebagai peristiwa kultural dan politis yang berdampak pada regenerasi, ekonomi lokal, hingga relasi sosial. Di tengah jargon pembangunan dan investasi hijau, buku ini mengingatkan bahwa “hijau” tanpa keadilan sosial adalah ilusi. Sebagaimana dicatat Erwin Basrin: “Tanah bukan sekadar ruang ekonomi, ia adalah identitas.”[5]
Buku Malin Deman: Dalam Pusaran Konflik Agraria karya Erwin Basrin merupakan dokumentasi reflektif dan advokatif atas konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat Malin Deman dengan perusahaan perkebunan sawit PT Daria Dharma Pratama. Buku ini membuka tabir panjangnya perjuangan masyarakat yang selama bertahun-tahun mempertahankan hak atas tanah warisan leluhur mereka yang kemudian diklaim dan dikuasai oleh perusahaan melalui skema HGU (Hak Guna Usaha) yang difasilitasi negara. Penulis mengungkap bagaimana masyarakat, yang sebelumnya hidup dari bertani secara mandiri, justru dikriminalisasi ketika mempertahankan tanahnya, termasuk penangkapan dan intimidasi oleh aparat negara.
Keunggulan utama buku ini adalah pendekatan metodologisnya yang partisipatoris dan mendalam. Erwin Basrin tidak menulis dari jarak, tetapi hadir sebagai bagian dari perjuangan itu sendiri. Ia mengumpulkan narasi dari pengalaman langsung sebagai pendamping masyarakat, menggali arsip-arsip kebijakan, serta melakukan wawancara dengan warga terdampak. Pendekatan ini membangun narasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga penuh empati. Ia tidak sekadar “mewakili” suara komunitas, tetapi berjalan bersama mereka dalam menghadapi ketidakadilan struktural yang menyelimuti sistem hukum dan tata kelola agraria Indonesia.
Secara keseluruhan, buku ini adalah catatan penting bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana relasi kuasa, hukum, dan kapital bekerja di tingkat lokal, serta bagaimana masyarakat adat bertahan dan melawan dalam keterbatasan. Malin Deman memperlihatkan bahwa konflik agraria bukan sekadar sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga pertarungan antara logika legal-formal negara dengan logika sosial-budaya masyarakat lokal. Dalam konteks ini, buku ini bukan hanya berfungsi sebagai karya dokumentasi, tetapi juga sebagai alat perlawanan dan inspirasi bagi gerakan keadilan agraria di Indonesia.
Sebagai refleksi akhir, Malin Deman adalah panggilan untuk tidak lagi memandang hukum sebagai alat netral. Ia harus ditantang, ditafsir ulang, dan diklaim kembali oleh mereka yang terdampak. Buku ini adalah upaya menggeser narasi dominan dan menghadirkan suara dari pinggiran.
[1] Basrin, E. (2024). Malin Deman: Dalam Pusaran Konflik Agraria, hlm. 8.
[2] Ibid., hlm. 45.
[3] Ibid., hlm. 63.
[4] Santos, B. de S. (2002). Toward a New Legal Common Sense. London: Butterworths LexisNexis.
[5] Basrin, E. (2024). Malin Deman: Dalam Pusaran Konflik Agraria, hlm. 91.
