Oleh Pramasti Ayu Kusdinar
Kamis 23 Oktober 2025, akhirnya kami bertemu lagi dengan nelayan dari desa Merpas dan Linau. Kali ini mereka yang menyambangi kami di Kota Bengkulu, melaksanakan janji temu kami untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan konflik yang dihadapi oleh nelayan dari dua desa tersebut. Dua minggu sebelum pertemuan ini berlangsung di Kota Bengkulu, kami tim Akar melakukan diskusi dengan para pihak di Kabupaten Kaur berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut dan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Kami bertemu dengan nelayan, pengepul, enumerator, pemuda/i, Kelompok Usaha Bersama (KUB), kelompok perempuan, pemerintah desa juga Bupati Kaur, Sekda, Asisten III, Staf Ahli Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama dan Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Sejak tahun 2019 Akar menemani masyarakat dua desa pesisir ini, dengan segala dinamikanya yang kemudian sepakat untuk membuktikan kepada publik bahwa pengelolaan laut dan pesisir di tangan masyarakat jauh lebih baik ketimbang jatuh pada tangan-tangan lain yang mungkin lebih serakah. Tadi, ketika kami baru saja memulai diskusi, salah satu nelayan dari desa Linau menyampaikan bahwa selama ini mereka selalu merasa baik-baik saja mengelola wilayah laut dan pesisirnya, seperti seolah-olah leluhur mereka hanya menitipkan laut dalam keadaan yang damai dan tenang. Tidak ada ombak yang menghantam kapal sampai karam, tidak ada asin yang mengikis karang. Namun semenjak ada Akar, mereka baru menyadari bahwa ternyata selama ini mereka hidup seperti ikan, yang selalu tertipu dengan mata pancing nelayan.
Inilah indikasi yang kami maksud sebagai basis advokasi murni; bagi Akar advokasi itu bukanlah soal menang atau kalah, melainkan bagaimana masyarakat dapat menciptakan perubahan sosial yang transformatif, yang basisnya adalah kesadaran kritis, kesadaran kelas dan kesadaran akan bertindak. Atau seperti jargon taktis yang sering disebutkan oleh salah satu staf Akar Lobian yakni, berpikir sebelum bertindak, bertindak sesuai rencana. Dan dalam merespon hal tersebut, saya juga menyampaikan bahwa Akar menyadari psikologis masyarakat yang tertindas, yang umumnya tidak menyadari bahwa dia adalah korban. Masyarakat biasanya merasa bahwa kemiskinan, kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupannya merupakan hal-hal yang taken for granted, seolah-olah mereka dilahirkan dan ditakdirkan untuk ditindas, diintimidasi dan harus menerima semua bentuk kejahatan itu sebagai sesuatu yang normal bagi seorang nelayan. Dan Pak Sapri, nelayan desa Merpas mengkonfirmasi hal tersebut dengan menyampaikan masalah mereka yang berkaitan dengan limbah sawit. “Dulu, kami pikir limbah sawit itu bagus untuk ikan, kami berpikir limbah sawit adalah pupuk bagi ikan. Sampai kami akhirnya sadar, setelah sekian tahun lamanya, limbah sawit milik PT. Citra Bumi Selaras yang mengalir dari hulu sungai hingga ke muara tepi pantai Merpas telah merusak ekosistem laut kami. Ikan-ikan kami pergi. Laut kami kotor dan bau. Kapal-kapal nelayan rusak. Wilayah tangkap kami menyempit”. Jelas Pak Sapri.
Nelayan dari desa Linau rupanya juga menghadapi hal yang sama. Ruang hidupnya menyempit karena dampak dari limbah tambak udang yang jumlahnya tidak sedikit membentang di pantai-pantai Linau yang indah. Para pelaku usaha tambak ini membuang limbah ke laut dan menyebabkan ikan-ikan mati. Produksi perikanan di desa Linau menurun karena sumber penghidupan mereka juga berkurang akibat ekspansi tambak udang tersebut. Sehingga, pada kondisi inilah konflik antar nelayan dari dua desa itu muncul yakni yang terkonsentrasi pada klaim wilayah tangkap dan alat tangkap nelayan. Ini merupakan rekayasa sosial yang sengaja diciptakan oleh industri raksasa untuk mengamankan aset produksi mereka dengan menciptakan konflik horizontal antar nelayan. Sehingga nelayan disibukkan dengan pertarungan nyawa antar sesama mereka, sementara industri tetap menghasilkan pundi-pundi laba.
Dalam forum ini, saya meminta mereka mencurahkan semua keluahannya sebagai sesama nelayan. Mereka menyampaikan bahwa konflik ini bermula dari adanya keluhan nelayan desa Linau terhadap nelayan gurita desa Merpas yang menangkap ikan di wilayah perairan desa Linau. Hal ini menjadi masalah besar karena hasil tangkap nelayan gurita dari desa Merpas selalu terlalu banyak sehingga menurut mereka tidak ada gurita di esok hari yang tersisa untuk nelayan dayung di desa Linau. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis alat tangkap antar nelayan. Nelayan gurita di desa Linau merupakan nelayan tradisional yang hanya memancing gurita dengan benang dan kail dari atas perahu dayung, sehingga mereka dikenal dengan nelayan dayung. Sayangnya, perahu dayung yang berukuran tidak lebih dari 2 meter itu tidak bisa menyentuh tubir ombak. Padahal, rumah gurita atau yang mereka sebut dengan benawang kaite ini terletak di karang-karang sang pemecah ombak. Sehingga, nelayan dayung ini hanya menanti kemalangan gurita yang akan tertipu mata kailnya untuk kesekian kali.
Berbeda dari nelayan gurita dayung desa Linau, nelayan gurita dari desa Merpas dikenal dengan nelayan derijen. Mereka tidak memiliki perahu. Dan hanya menggunakan keahlian khusus yakni menyelam untuk menangkap gurita. Mereka menggunakan tombak besi untuk menangkap gurita tanpa bantuan alat selam apapun. Dengan keahlian selamnya, mereka dapat menembus tubir ombak dan menyelam hingga lebih dari 20 meter ke dalam laut. Dengan keahlian inilah mereka mampu menangkap gurita jauh lebih banyak ketimbang nelayan dayung di desa Linau.
Berdasarkan kondisi tersebut diatas, tipe konflik nelayan di dua desa ini dapat merujuk pada penjelasan Satria dkk (2002;166-170) yang menuliskan salah satu tipe konflik di kalangan nelayan adalah konflik agraria, yakni konflik yang terjadi akibat perebutan fishing ground: yang terjadi antarkelas, intra-kelas dan antara nelayan dengan non-nelayan. Sementara jika dilihat dari sudut pandang Rilus (2014; 35-36), konflik nelayan 2 desa ini masuk dalam tipe konflik alat tangkap; yakni konflik yang terjadi antara kelompok nelayan yang berbasis alat tangkap yang berbeda, tapi berada tingkat yang kurang lebih setara. Konflik alat tangkap ini dikenal dengan istilah “gear wars”. Namun, menurut hemat saya, apapun jenis tipe konflik yang mencuat di antara nelayan dua desa tersebut, hal tersebut bukanlah inti persoalannya. Karena sesungguhnya yang menciptakan konflik tersebut bukanlah alat tangkap atau wilayah tangkap mereka, melainkan himpitan industri raksasa kelapa sawit dan tambak udang yang milik segelintir orang yang sangat berkuasa di desa.
Selama kami diskusi, sebetulnya diskursus yang menguat adalah diskursus soal tragedy of the common diatas common pool resources dengan sifat pengelolaan yang open access. Tragedy of the common yang dikenalkan oleh Garret Hardin adalah sebuah peristiwa kehilangan danatau kehancuran sumber daya alam milik bersama yang terjadi karena setiap orang mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk diri sendiri, tetapi dampak kehancuran ditanggung bersama oleh semua pengguna. Fenomena ini terjadi pada sumber daya alam yang diakses atau oleh banyak orang atau open accsess seperti ikan di laut. Seperti yang dijelaskan oleh Erwin Basrin dalam artikel terakhirnya di website Akar yang berjudul; mengelola laut sebagai the commons; dari tragedi ke governance, yang menjelaskan bahwa salah satu jalan untuk menghentikan tragedy of the common ini adalah dengan membangun apa yang kemudian disebut dengan the common rules; atau seperangkat aturan bersama yang dibutuhkan untuk ‘menata’ sumber daya yang open access tersebut.
Namun, the common rules ini bukanlah perangkat aturan kami maksudkan bersumber dari atas ke bawah (top to bottom) atau yang bersifat suprastruktur, melainkan yang berasal dari dalam untuk keluar. Sebab, menurut pengakuan nelayan desa Linau, keterlibatan pemerintah dalam tata kelola laut atau pesisir di desanya malah memicu banyak masalah. Seperti misalnya diam-diam di desa sudah ada tambak udang, dan sebagian wilayah pesisir Linau masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Hal ini terjadi karena negara dan para pengusaha melihat sumber daya yang ada di desa hanya sebagai space; ruang hampa tanpa huni, padahal sumber daya tersebut bagi masyarakat adalah place; ruang hidup yang terbentuk karena ikatan kebudayaan dan tradisi yang terpahat karena interaksi mereka dengan alamnya. Untuk itu, seperangkat aturan ini mestilah dibuat oleh masyarakat itu sendiri yang memiliki seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai kelokalan yang berpijak pada prinsip-prinsip inklusifitas dan berkelanjutan.
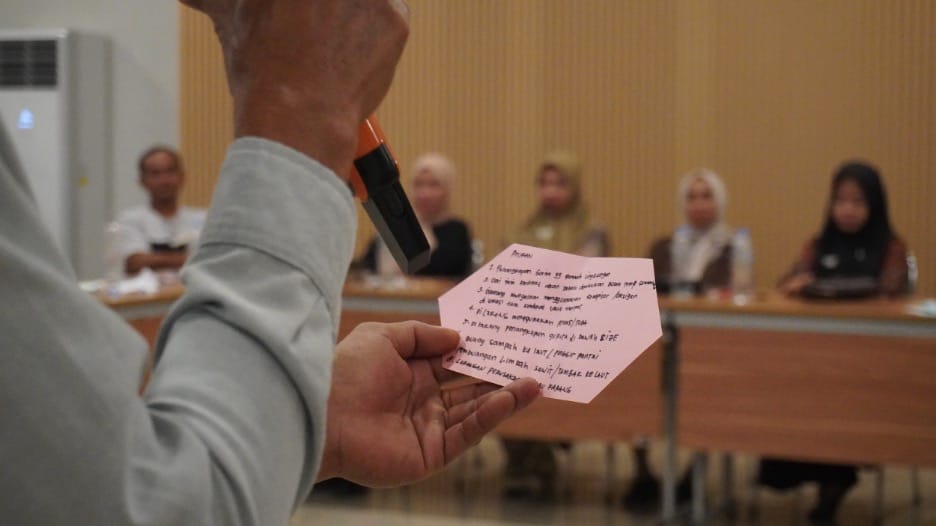
“Kami bukannya tidak mau berbagi laut kami, karena selama ini kita adalah saudara. Kita selalu berbagi apa yang kita makan.” ucap Rio. Deki, nelayan dayung desa Linau ini juga menambahkan, “Bayangkan kalau tidak ada pembatasan, ikan-ikan akan habis karena ditangkap terus tanpa memberikannya waktu untuk tumbuh, semua ikan akan habis, dan kita akan kelaparan”.
Jadi, resolusi yang mereka rumuskan dalam forum ini adalah tidak ada pembatasan wilayah tangkap. Setiap nelayan boleh memancing dan menangkap ikan di manapun mereka suka, namun dengan syarat, setiap nelayan harus saling menghormati nilai dan tradisi nelayan lain. Misal, jika nelayan Linau memancing dengan pancing dan perahu, maka nelayan lain yang datang ke wilayah tangkap nelayan desa Linau harus menggunakan alat tangkap yang sama dengan nelayan dayung di Linau. Pun sebaliknya, jika nelayan dari Linau ingin menangkap benur di desa Merpas, maka ia harus menangkap dengan cara nelayan Merpas menangkap benur, tidak menggunakan jaring atau alat tangkap lain yang merusak karang.
Melalui pertemuan inilah kami semakin yakin untuk membangkan diskursus locally managed marine area (LMMA) atau Community Based Marine Management (CBMM) yang memperkuat legitimasi pengelolaan sumber daya laut ini ditangan masyarakat. Namun, masalah lainnya yang kami temui adalah menguatnya otoritas pemerintah terhadap sumber daya laut dan wilayah pesisir masyarakat di desa membuat otonomi dan kepercayaan diri masyarakat terdapat axis mundi-nya melemah. Sehingga, dalam konteks ini Akar Law Office mengambil peran untuk memperkuat kesadaran masyarakat nelayan di desa terhadap haknya dan bagaimana masyarakat dapat membela hak-nya tersebut dihadapan hukum.
Pada perjalanan kami menuju desa Merpas dan desa Linau beberapa minggu lalu, kami melihat bahwa kebanyakan nelayan merasa putus asa dan takut ketika berhadapan dengan hukum. Bagi mereka, hukum berarti punishment. Masyarakat menganggap, setiap orang yang ‘berurusan’ dengan hukum adalah orang yang bersalah. Hukum menaklukan masyarakat. Padahal, menurut Ricki Direktur Akar Law Office, hukum seharusnya digunakan oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka, yang bukan hanya sebagai nelayan tetapi juga sebagai masyarakat desa. Berikut beberapa payung hukum yang direkomendasikan untuk dipahami oleh nelayan di Indonesia untuk melindungi dan membela hak-nya serta mensejahterakan keluarga dan kelompoknya :
- UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No.45 Tahun 2009
- UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No.1 Tahun 2014
Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum dilakukan secara maksimal. Masih banyak hal yang menjagal kesejahteraan nelayan. Untuk itulah masyarakat harus belajar memahami hak-haknya dan dan perangkat hukum yang harusnya bisa mereka gunakan sebagai senjata untuk melawan ketidakadilan. Dan hal tersebut haruslah berangkat dari kesadaran untuk dirinya sendiri atau class for it self yang menjadi awal dari perjuangan kelas nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagai kelompok marginal. “It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness”, tulis Marx sebagai kritik terhadap Ekonomi Politik. Marx, dan kami semua percaya bahwa kesadaran kelas akan membawa kita pada suatu perubahan sosial yang signifikan yakni sumber daya laut dan wilayah pesisir yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.
