Resensator: Erwin Basrin
Berebut Makan: Politik Baru Pangan adalah terjemahan bahasa Indonesia dari buku Feeding Frenzy: The New Politics of Food (2013) karya Paul McMahon. Buku ini lahir dari kegelisahan atas krisis pangan global pasca 2008, ketika harga bahan pangan melonjak tajam dan menimbulkan gejolak di banyak negara. McMahon, seorang pakar kebijakan pangan yang pernah bekerja di FAO, menyajikan analisis menyeluruh tentang mengapa sistem pangan dunia mengalami krisis dan bagaimana politik global turut menentukan siapa yang kenyang dan siapa yang kelaparan. Ulasan kritis ini akan membahas argumen utama McMahon, pendekatan teoretis dan metodologis yang ia gunakan, konteks politik pangan global yang melatarbelakangi karyanya, kekuatan dan kelemahan argumen-argumennya, serta relevansi buku ini bagi situasi pangan dan politik agraria di Indonesia masa kini.
Seharian membaca buku ini, saya mencoba untuk menulis ringkasan argument utama buku ini. McMahon berargumen bahwa krisis pangan global bukan disebabkan oleh kurangnya produksi pangan secara absolut, melainkan oleh kegagalan politik, ekonomi, dan sosial dalam mendistribusikan dan mengelola pangan. Ia menolak pandangan Malthusian yang menyalahkan ledakan populasi atas kelaparan. McMahon menunjukan bahwa secara global sebenarnya cukup lahan dan sumber daya untuk memberi makan populasi dunia yang terus bertambah yang bahkan terdapat sekitar 1,3 miliar hektar lahan terbuka yang masih berpotensi untuk pertanian, setara 80% dari luas lahan yang saat ini sudah ditanami. Masalahnya, potensi tersebut tidak tergarap karena berbagai hambatan struktural: infrastruktur yang buruk, pasar yang tidak berfungsi, kurangnya akses petani miskin pada pengetahuan dan teknologi, keterbatasan pembiayaan, ketidakjelasan hak atas tanah, hingga kebijakan dan tata kelola yang gagal mendukung petani kecil. Akibatnya, produktivitas pertanian di banyak negara berkembang tetap rendah bukan karena alam yang tidak mendukung, tetapi karena kegagalan kebijakan dan institusi.
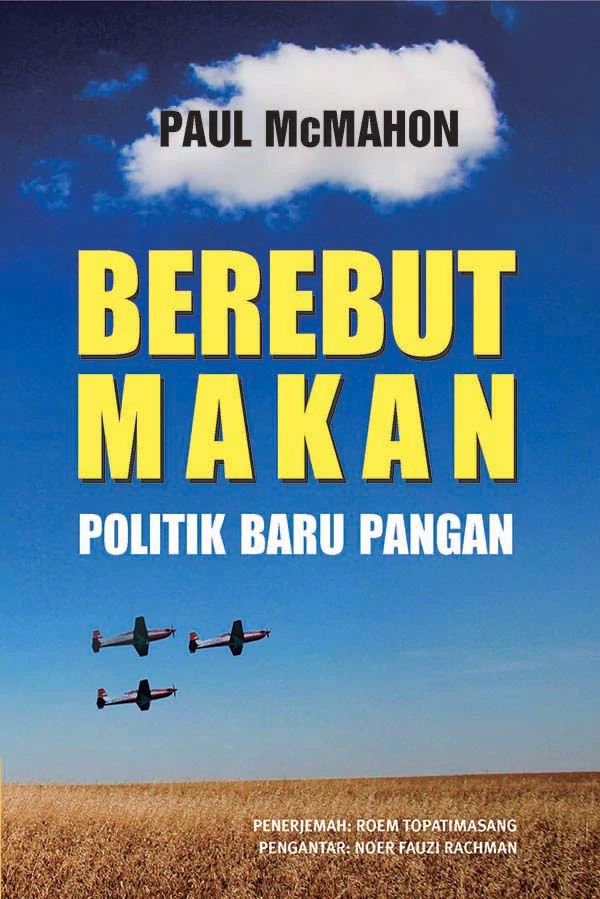
McMahon menekankan bahwa kelaparan adalah hasil keputusan politik, sejalan dengan ungkapan Hira Jhamtani dalam pengantar edisi Indonesia: “Lapar adalah keputusan politik”. Data global menunjukkan ironi dimana seperdelapan penduduk dunia menderita kelaparan, sementara di sisi lain produksi pangan berlebih membuat banyak orang mengalami obesitas. Masalahnya bukan semata-mata kurangnya teknologi pertanian, melainkan rangkaian kebijakan yang memperburuk ketimpangan akses terhadap pangan. Dalam perjalanan sejarah, pangan kerap dijadikan alat politik: misalnya di era Perang Dingin, surplus pangan Amerika Serikat dijadikan senjata diplomatik melalui program Food for Peace untuk mempengaruhi negara-negara berkembang agar berpihak ke blok Barat. Contoh ini menegaskan bahwa siapa yang lapar dan siapa yang kenyang sering ditentukan oleh pertarungan kekuasaan dalam politik internasional.
Buku Berebut Makan mengurai penyebab krisis pangan mutakhir secara komprehensif. McMahon membedah sejumlah faktor pemicu lonjakan harga pangan dunia, antara lain perubahan pola konsumsi (diet yang semakin kaya protein hewani seiring meningkatnya pendapatan penduduk dunia), frekuensi cuaca ekstrem yang meningkat akibat perubahan iklim, alih fungsi pangan menjadi biofuel, serta batas kapasitas ekologis di banyak tempat. Tidak ada satu pun faktor tunggal yang sepenuhnya menjelaskan krisis. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan “badai sempurna” yang mengguncang pasar pangan global. McMahon juga menyoroti respon panik banyak negara ketika krisis terjadi: misalnya pada krisis 2007-2008 dan 2010-2011, beberapa negara produsen utama memberlakukan larangan ekspor pangan secara tiba-tiba (dipicu oleh Rusia pada 2010), sementara negara importir melakukan panic buying di pasar internasional. Tindakan-tindakan sepihak ini menciptakan efek domino yang memperburuk kelangkaan dan memicu kerusuhan di lebih dari 30 negara, bahkan berkontribusi memantik Arab Spring di Timur Tengah. McMahon menggambarkan situasi ini bak dilema narapidana di mana langkah proteksionis masing-masing negara justru merugikan kepentingan bersama dalam stabilitas pangan.
Sebagai inti argumennya, McMahon menegaskan kemendesakan reformasi sistem pangan global. Ia menunjukkan bahwa pasar komoditas pangan dewasa ini tidak dikendalikan untuk kepentingan kemanusiaan, melainkan rentan dimainkan oleh spekulan finansial demi keuntungan semata. Setelah krisis finansial 2008, melimpahnya modal mencari keuntungan singkat telah membanjiri pasar pangan dan energi, membuat harganya tak terkelola dan mudah dimanipulasi. Transaksi berkecepatan tinggi (high-frequency trading) memungkinkan spekulan mengguncang harga komoditas pangan dalam sekejap tanpa memedulikan dampaknya bagi manusia. Dominasi segelintir korporasi multinasional (dikenal sebagai “ABCD”: ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus) atas perdagangan pangan dunia juga menambah masalah struktural, karena rantai pasok global berada di bawah kendali oligopoli. Selain itu, McMahon mengupas fenomena pencaplokan lahan besar-besaran (land grabbing) pasca krisis pangan. Negara kaya pangan dan investor swasta berlomba mengakuisisi lahan subur di Afrika, Asia, dan Amerika Latin untuk menjamin pasokan bagi dirinya sendiri. Ia memperingatkan bahwa “booming” land grab, misalnya ketika negara-negara Teluk membeli lahan di Afrika merupakan tren berbahaya yang bisa memicu konflik dan memperburuk ketimpangan global.
Di tengah berbagai masalah tersebut, Berebut Makan tidak berakhir dengan nada pesimis. Berbeda dengan para “peramal kiamat” yang meramalkan keruntuhan tak terhindarkan dari sistem pangan, McMahon percaya krisis ini dapat diatasi. Buku ini menawarkan secercah harapan dengan memaparkan solusi-solusi menuju sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Di bab terakhir, McMahon mengajukan sebuah “resep” berisi empat elemen kunci (disebut oleh Guardian sebagai rencana ber-empat bahan untuk memberi makan planet ini) yang harus dijalankan bersama-sama oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk memperbaiki politik pangan dunia. Empat langkah utama tersebut meliputi: (1) mendukung dan meningkatkan produksi petani kecil di negara-negara miskin, (2) menerapkan prinsip-prinsip agroekologi dalam sistem pertanian agar lebih ramah lingkungan dan berpihak pada komunitas lokal, (3) mengendalikan pasar keuangan agar berorientasi pada tantangan nyata (misalnya dengan regulasi yang mencegah spekulasi berlebihan dan mengarahkan investasi ke peningkatan produksi pangan riil), dan (4) melakukan penyesuaian terhadap tren harga pangan yang cenderung meningkat dengan beralih menuju ekonomi berbasis hayati (bio-based economy) melalui inovasi ilmu pengetahuan dan bioteknologi. Menurut McMahon, jika langkah-langkah ini dijalankan, dunia sebenarnya mampu memberi makan 9 miliar orang di tahun 2050 secara layak. Inti pesan buku ini: krisis pangan adalah produk kebijakan yang keliru, sehingga solusi utamanya pun terletak pada perubahan kebijakan dan struktur ekonomi-politik, bukan semata pada usaha meningkatkan produksi pangan.
Pendekatan Teoretis dan Metodologis
Secara metodologis, McMahon menggunakan pendekatan interdisipliner dengan sejarah dan ekonomi politik sebagai tulang punggung analisis. Buku ini dimulai dengan survei sejarah sistem pangan global, melacak evolusi pertanian dari era pra-industri hingga era Revolusi Hijau dan globalisasi. Pendekatan historis ini dipakai untuk menunjukkan bagaimana kebijakan agraria dan perdagangan pangan sejak masa kolonial telah menciptakan kesenjangan yang besar antar petani dan antar bangsa. Sebagai contoh, McMahon (didukung oleh pengantar Noer Fauzi Rachman) mengingatkan bahwa sejak kolonialisme, penduduk Eropa telah menikmati “pangan global” gula, teh, kopi, rempah dengan biaya penderitaan petani di koloni seperti Jawa dan India. Penguasaan sumber pangan melalui politik agraria kolonial inilah cikal bakal ketimpangan sistem pangan modern. Landasan teoretis semacam ini selaras dengan kerangka rezim pangan (food regime theory) ala Philip McMichael, yang memandang rantai pasokan pangan dunia sebagai arena pertarungan kekuatan politik-ekonomi. Meskipun McMahon sendiri tidak menulis dalam jargon akademik, perspektifnya menangkap esensi bahwa urusan produksi hingga konsumsi pangan tidak pernah lepas dari hubungan kekuasaan global.
Selain sejarah, McMahon mengandalkan analisis data dan studi kasus aktual untuk mendukung argumennya. Ia menyajikan banyak fakta dan statistik misalnya perbandingan ketersediaan lahan, produktivitas pertanian, angka konsumsi dan pemborosan pangan, hingga porsi penduduk laparan yang diolah dari sumber-sumber internasional terpercaya. Penyajian data dalam buku ini dikemas dengan gaya populer ilmiah yang mudah dipahami. Saya mencatat bahwa penjelasan McMahon sangat jernih dan bebas jargon, sehingga pembaca umum pun dapat mengikutinya tanpa latar belakang teknis khusus. Sebagai contoh, pembahasan mengenai perdagangan berjangka (futures) dan peran spekulan di pasar pangan disampaikan secara ringkas namun terang, bahkan dinilai sebagai salah satu paparan terbaik tentang topik tersebut. Pendekatan semacam ini mencerminkan metodologi McMahon yang menekankan klaritas dan edukasi pembaca, ketimbang terjebak istilah teoretis yang kompleks.
Dari segi teoritis, McMahon mengambil posisi pragmatik kritis. Ia tidak secara eksplisit mengusung teori ekonomi politik tertentu, namun kerangka pikirnya dekat dengan tradisi kritis terhadap neoliberalisme. Ini terlihat dari kritiknya terhadap pasar bebas tanpa regulasi di sektor pangan. McMahon sepakat bahwa pangan “bukan komoditas biasa” dan karena itu menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar justru menimbulkan inefisiensi dan krisis. Pandangan ini berakar dari teori ekonomi politik yang menilai pasar pangan global telah didistorsi oleh kekuatan korporasi raksasa dan negara-negara kuat demi keuntungan sepihak. Sementara itu, ia juga mengapresiasi gagasan-gagasan gerakan kedaulatan pangan (food sovereignty) yang menekankan pentingnya kemandirian komunitas petani, keadilan akses tanah, dan perlindungan terhadap pertanian skala kecil. Meskipun demikian, McMahon tidak sepenuhnya mengadopsi agenda radikal gerakan kedaulatan pangan. Ia memadukan unsur kritik struktural dengan solusi reformis yang bisa diterapkan dalam kerangka sistem yang ada. Pendekatan “jalan tengah” ini tercermin dari rekomendasinya yang menggabungkan teknologi tinggi (bioteknologi, reformasi pasar keuangan) dengan pendekatan kerakyatan (pemberdayaan petani kecil, agroekologi). Secara metodologis, kombinasi perspektif inilah yang menjadi kekuatan buku ini: analisis didukung data faktual yang luas, kerangka historis yang kuat, serta sintesis berbagai arus pemikiran (neomalthusian vs anti-malthusian, neoliberal vs kedaulatan pangan) untuk merumuskan jalan keluar yang komprehensif.
Konteks Politik Pangan Global yang Melatarbelakangi
Untuk memahami buku Berebut Makan, kita perlu melihat konteks politik pangan global satu dekade terakhir yang menjadi latar belakang penulisannya. Periode 2007-2013 adalah masa ketika isu ketahanan pangan global mencuat kembali ke panggung utama, dipicu oleh krisis harga pangan dunia. Pada tahun 2007-2008, harga komoditas pangan pokok (seperti gandum, beras, jagung) melonjak hingga level tertinggi dalam beberapa dekade, memicu kerusuhan pangan di lebih dari 30 negara dari Asia, Afrika, hingga Karibia. Situasi serupa terulang pada 2010-2011. Krisis ini terjadi setelah sekian lama dunia menikmati pangan murah; para analis menyebutnya kemungkinan akhir dari “era pangan murah” dan masuk ke “normal baru” harga tinggi. Faktor penyebabnya kompleks: badai faktor ekonomi, iklim, dan politik. Gagal panen akibat cuaca buruk (misalnya kekeringan parah di Rusia tahun 2010) mengurangi suplai gandum global. Lonjakan harga minyak bumi membuat biaya produksi dan transportasi pangan naik, serta mendorong negara-negara Barat mengalihkan jagung dan tebu menjadi biofuel sebagai suatu kebijakan yang oleh banyak pihak dituduh turut menyedot pasokan pangan. Permintaan dari konsumen negara berkembang yang kian makmur (terutama Tiongkok, India) meningkat pesat, terutama untuk daging dan produk hewani yang membutuhkan pakan bijian. Ditambah lagi, setelah krisis keuangan 2008, investor finansial mencari ladang spekulasi baru dan menemukan komoditas pangan sebagai salah satu tujuan investasi, sehingga modal spekulatif membanjiri bursa komoditas agrikultur.
Konteks politik global juga turut memperparah keadaan. Bukannya bekerjasama menghadapi krisis, banyak negara justru mengambil kebijakan unilateral defensif. Produsen pangan besar seperti Rusia, India, dan Vietnam menerapkan larangan ekspor beras atau gandum untuk melindungi konsumen domestik dari kelangkaan. Sementara itu, negara importir panik dan membeli dalam jumlah besar di pasar internasional untuk stok, yang malah mendorong harga naik lebih tinggi. Tindakan kolektif semacam ini, seperti dicatat McMahon, adalah resep pasti menuju kekacauan, analog dengan tetangga membiarkan tetangganya kelaparan demi menyelamatkan diri sendiri. Hasil akhirnya adalah gangguan politik: protes massa dan instabilitas. McMahon mengungkap bahwa krisis pangan 2008 berkontribusi menjatuhkan beberapa pemerintahan dan menyumbang kemarahan rakyat yang memicu Arab Spring 2011. Dalam tataran global, forum-forum seperti G8/G20 buru-buru mengagendakan pembahasan ketahanan pangan, namun upaya kolaboratif nyata masih tertinggal di belakang kepentingan nasional masing-masing.
Krisis pangan juga mendorong pergeseran geopolitik pangan. Negara kaya berduit namun miskin lahan (seperti negara-negara Teluk, China, Korea Selatan) mengambil langkah kontroversial dengan berinvestasi langsung pada lahan pertanian di luar negeri, sebuah gelombang land grabbing yang utamanya menyasar Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Tujuannya untuk mengamankan produksi pangan di lahan tersebut bagi kebutuhan mereka sendiri. Langkah ini dipandang McMahon sebagai “perebutan makan” dalam arti literal: pihak yang kuat secara finansial berusaha merebut sumber pangan di wilayah lain, berpotensi menggeser hak petani lokal dan kedaulatan pangan negara target. Kasus terkenal misalnya rencana perusahaan Korea untuk menggarap jutaan hektar lahan di Madagaskar, atau perusahaan investasi dari Timur Tengah yang membeli lahan di Sudan dan Indonesia. Selain itu, investor swasta dan hedge funds juga ikut membeli lahan pertanian sebagai aset spekulatif. Semua ini menandakan munculnya “politik baru pangan”, istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi di mana pangan bukan lagi urusan supply-demand tradisional, tapi telah menjadi isu strategis lintas negara yang melibatkan diplomasi, keamanan nasional, hingga bisnis global.
Konteks lain yang melatarbelakangi buku ini adalah kesadaran akan dampak lingkungan dari pertanian modern. Selama abad ke-20, revolusi hijau dan pertanian industrial berhasil meningkatkan produksi, tapi dengan biaya ekologis: penggunaan masif pupuk kimia dan pestisida, penyedotan air tanah berlebihan, deforestasi untuk lahan sawah dan ladang, hingga emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. McMahon mencatat bahwa sistem pertanian modern “dibangun di atas energi fosil murah” mulai dari traktor hingga pabrik pupuk bergantung pada minyak dan gas. Konsekuensinya, ketika harga energi naik atau sumber energi terancam, sistem pangan ikut terguncang. Selain itu, praktek monokultur dan intensifikasi ekstrim menyebabkan degradasi lahan: tanah menjadi tandus, keanekaragaman hayati menurun, dan hama penyakit kian kebal obat.
Krisis lingkungan ini menantang keberlanjutan produksi pangan jangka panjang. Oleh karenanya, diskursus global mulai bergeser ke arah pangan berkelanjutan. Banyak pihak menyerukan transisi ke praktek organik atau agroekologi, sementara kubu lain mendorong solusi teknologi tinggi seperti rekayasa genetik tanaman untuk meningkatkan efisiensi. McMahon menempatkan bukunya di tengah perdebatan tersebut, dengan sikap menimbang berbagai klaim: ia skeptis terhadap solusi tunggal yang terlalu “hijau” ataupun terlalu “teknokratis”. Dalam Berebut Makan, berbagai argumen dari veganisme, pertanian organik, GMO, perdagangan bebas, hingga reforma agraria ditinjau dan dipilah secara kritis. Singkatnya, buku ini lahir di tengah pergulatan mencari model politik pangan baru pasca krisis, ketika konsensus lama runtuh dan aneka ide bermunculan untuk mengatasi tantangan memberi makan dunia di abad ke-21.
Relevansi Buku terhadap Kondisi Pangan dan Politik Agraria di Indonesia
Isu-isu yang dibahas dalam Berebut Makan memiliki resonansi kuat dengan kondisi pangan dan agraria Indonesia. Sebagai negara agraris berpenduduk besar, Indonesia berada di persimpangan antara potensi swasembada pangan dan tantangan ketahanan pangan akibat dinamika politik-ekonomi global. Buku ini menawarkan kerangka analisis yang berguna untuk memahami dan mengkritisi kebijakan pangan Indonesia.
Pertama, argumen McMahon bahwa kelaparan dan kemiskinan petani adalah persoalan politik, bukan semata produksi, sangat relevan di Indonesia. Meskipun Indonesia mampu swasembada beras pada era 1980-an, hingga kini masalah gizi buruk dan kerawanan pangan masih ada di kantong-kantong kemiskinan, terutama di wilayah Indonesia timur. Kondisi ini menggarisbawahi tesis “lapar adalah keputusan politik”, akses pangan masyarakat miskin di Indonesia seringkali terhambat oleh kebijakan yang kurang berpihak. Misalnya, ketika harga beras dunia naik, pemerintah kadang ragu membuka keran impor demi melindungi petani lokal, tapi di sisi lain stok beras nasional tidak cukup untuk menurunkan harga, membuat konsumen miskin terpukul. Ini semacam dilema kebijakan yang cocok dengan gambaran McMahon tentang negara-negara yang terjebak “malakama” saat krisis pangan. Buku ini mendorong kesadaran bahwa solusi jangka panjang bukan sekadar menambah produksi (Indonesia sudah surplus beras beberapa kali namun masalah distribusi tetap ada), melainkan memperbaiki tata niaga dan jaring pengaman sosial agar kelompok rentan tidak menjadi korban pertama gejolak harga.
Kedua, rekomendasi McMahon untuk memberdayakan petani kecil dan menerapkan agroekologi sejalan dengan kebutuhan pembaruan agraria di Indonesia. Sebagian besar petani Indonesia adalah petani skala kecil dengan lahan sempit. Produktivitas mereka rendah bukan karena mereka malas atau bodoh, tetapi karena kurang dukungan: akses terbatas pada kredit, penyuluhan minim, infrastruktur irigasi buruk, dan tanah sering terancam alih fungsi. McMahon mencatat faktor-faktor seperti ini sebagai penyebab “kegagalan produksi” di negara berkembang, dan itu cocok dengan kondisi banyak desa Indonesia. Karena itu, dorongan agar pemerintah menginvestasikan sumber daya untuk petani kecil adalah masukan langsung bagi Indonesia. Program reforma agraria dan distribusi lahan yang dicanangkan pemerintah, misalnya, dapat memperoleh justifikasi dari argumen McMahon bahwa petani kecil yang diberdayakan mampu meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus mengentaskan kemiskinan. Pendekatan agroekologi seperti pertanian organik, diversifikasi tanaman, penggunaan benih lokal mulai marak di Indonesia melalui gerakan tani dan LSM. Buku ini memperkuat argumen bahwa pendekatan tersebut bukan romantisme belaka, melainkan bagian penting dari solusi global untuk keberlanjutan pangan. Di tengah ancaman degradasi lahan (contoh nyata: kerusakan ekosistem di Jawa akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan sejak Revolusi Hijau), transisi ke praktek agroekologi di Indonesia semakin mendesak. McMahon menyediakan narasi global yang mendukung kebijakan pro-agroekologi di tingkat nasional.
Ketiga, konteks politik pangan global yang dipaparkan buku ini membantu menjelaskan posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Indonesia pernah mengalami sendiri dampak krisis pangan global 2008: lonjakan harga kedelai impor memukul produsen tahu-tempe domestik, memicu protes dan mendorong pemerintah mencari alternatif sumber kedelai. Kasus ini menunjukkan betapa terhubungnya Indonesia ke pasar pangan dunia sesuai dengan analisis McMahon bahwa volatilitas harga komoditas strategis dapat menghantam negara manapun yang bergantung impor. Selain itu, tren land grabbing global menemukan cerminnya di Indonesia, meskipun pola dan pelakunya berbeda. Indonesia bukan target masif land grab oleh negara asing seperti kasus Afrika, tetapi konflik perebutan lahan di sini terjadi antara korporasi (baik swasta nasional maupun asing) dengan petani lokal. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, HTI, tambang, dan proyek food estate kerap melibatkan pengambilalihan lahan berskala besar yang mengancam kedaulatan pangan lokal. Sebagai contoh, pada 2010-an pernah diwacanakan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua, dengan investor dari Timur Tengah dan Asia, yang menargetkan lebih dari sejuta hektar lahan untuk produksi pangan industri. Wacana ini sejalan dengan fenomena yang digambarkan McMahon: negara kaya modal berusaha mengamankan pasokan dengan memanfaatkan lahan di negara berkembang. Reaksi penolakan dari kelompok masyarakat adat dan LSM di Indonesia terhadap MIFEE menunjukkan kesadaran akan risiko model tersebut, risiko yang juga diulas dalam buku Berebut Makan sebagai “kecerobohan berbahaya” jika tidak diatur adil.
Keempat, buku ini relevan untuk menggali perdebatan kebijakan pangan di Indonesia antara pendekatan pasar vs kedaulatan pangan. Pemerintah Indonesia di satu sisi terikat pada perdagangan internasional (WTO) yang menuntut liberalisasi, di sisi lain konstitusi mengamanatkan bahwa “pangan dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam praksis, kita melihat tarik-menarik: kebijakan impor pangan menjadi polemik politis rutin – ada kubu yang pro-pasar bebas demi stabilisasi harga konsumen, ada kubu yang pro-swasembada demi melindungi petani. McMahon memberikan penilaian kritis bahwa perdagangan bebas bukan solusi otomatis untuk masalah pangan. Ia mendukung proteksi tertentu dan peran negara aktif, yang sejalan dengan semangat “kedaulatan pangan” yang belakangan diadopsi dalam Undang-Undang Pangan No.18/2012 di Indonesia. Konsep food sovereignty yang didorong LSM dan organisasi tani di Indonesia menemukan justifikasi akademis dalam buku ini: misalnya, kebutuhan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi dan ekspansi korporasi, atau keberpihakan pada petani lokal dalam distribusi pupuk dan benih. Sementara itu, McMahon juga tidak menafikan peran teknologi dan investasi, hal ini relevan dengan agenda pemerintah memodernisasi pertanian (seperti program mekanisasi, pembangunan rice estate di Kalimantan, atau penerapan varietas unggul).
Terakhir, relevansi buku ini tampak dalam hal tantangan masa depan pangan Indonesia. Menuju 2050, penduduk Indonesia akan mendekati 320 juta jiwa. Tekanan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi (kita lihat konsumsi daging di perkotaan meningkat, fast food makin digemari) akan mirip dengan tren global yang McMahon bahas. Kita juga sudah menghadapi pemborosan pangan. Data Bappenas mencatat jutaan ton makanan terbuang tiap tahun di Indonesia, sementara masalah gizi tetap ada. Perubahan iklim pun mulai dirasakan: musim tanam kacau, banjir dan kekeringan mengancam produksi beras. Dalam konteks ini, Berebut Makan memberikan peringatan dini: tanpa perubahan kebijakan, sistem pangan rentan kolaps di tengah tekanan ini. Sebaliknya, jika rekomendasi seperti McMahon dijalankan – investasi di pertanian berkelanjutan, pengurangan ketergantungan impor pakan dan pangan melalui diversifikasi lokal, pengendalian rantai pasok oleh pemerintah untuk mencegah spekulasi harga (misal memperkuat Bulog), serta edukasi publik untuk mengurangi pemborosan dan konsumsi tidak sehat, Indonesia bisa lebih tangguh menghadapi tantangan pangan. Buku ini, walaupun berbasis konteks global, seolah berbicara langsung kepada Indonesia: sebuah negeri dengan sumber daya melimpah namun masih harus “berebut makan” antara rakyat kecil, korporasi, dan kepentingan global. Dengan memahami insight dari Paul McMahon, para pemangku kepentingan di Indonesia dapat melihat masalah pangan domestik bukan sebagai fenomena terisolasi, tapi bagian dari dinamika politik-ekonomi dunia yang perlu diantisipasi dengan kebijakan visioner.
