Resensator: Erwin Basrin
Ketika menyesap secangkir kopi hangat di pagi hari, pernahkah kita membayangkan pahit-getir sejarah di balik biji kopi Nusantara? Buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720–1870 karya Jan Breman, seorang sejarawan dan sosiolog Belanda mengajak kita menelusuri “halaman hitam” sejarah itu dengan pendekatan ilmiah sekaligus empati sosial bagaimana perkebunan kopi dibangun di Priangan (Jawa Barat) dengan keringat dan penderitaan penduduk pribumi. Tujuan utamanya bukan sekadar merekam peristiwa masa silam, tetapi juga memberi konteks pada kondisi masa kini“Pengetahuan masa lalu diperlukan untuk lebih mengetahui masa kini dan masa depan”. Ulasan kritis saya ini akan membahas isi utama buku, argumen pokok Breman tentang sistem kerja paksa kolonial, kritiknya terhadap ekonomi kolonial Hindia-Belanda, dan relevansi temuan Breman bagi persoalan agraria dan perburuhan Indonesia dewasa ini.
Buku ini secara kronologis memaparkan lahir, berkembang, dan dampak dari Prianger Stelsel, sistem tanam paksa kopi di wilayah Priangan selama hampir satu setengah abad kekuasaan kolonial Belanda. Breman membuka kisah sejak awal abad ke-18 ketika VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda) memperkenalkan bibit kopi arabika ke Jawa.
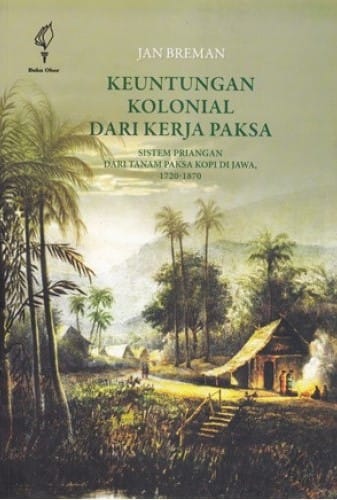 Gubernur Jenderal Joan van Hoorn pada 1696 menanam bibit kopi pertama di sekitar Batavia, namun baru di tanah Priangan-lah kopi menemukan lahan subur. Breman menunjukkan bagaimana pada dekade awal 1700-an, para bupati Priangan seperti Raden Aria Wira Tanu III di Cianjur mulai diwajibkan menanam dan menyerahkan kopi kepada VOC. Hasilnya menakjubkan bagi Belanda. Hanya dalam kurun 20 tahun, Jawa berubah dari pengimpor menjadi pengekspor utama kopi dunia. Istilah “secangkir Jawa” bahkan menjadi populer di Eropa merujuk kopi kualitas tinggi dari Priangan.
Gubernur Jenderal Joan van Hoorn pada 1696 menanam bibit kopi pertama di sekitar Batavia, namun baru di tanah Priangan-lah kopi menemukan lahan subur. Breman menunjukkan bagaimana pada dekade awal 1700-an, para bupati Priangan seperti Raden Aria Wira Tanu III di Cianjur mulai diwajibkan menanam dan menyerahkan kopi kepada VOC. Hasilnya menakjubkan bagi Belanda. Hanya dalam kurun 20 tahun, Jawa berubah dari pengimpor menjadi pengekspor utama kopi dunia. Istilah “secangkir Jawa” bahkan menjadi populer di Eropa merujuk kopi kualitas tinggi dari Priangan.
Di balik lonjakan ekspor itu tersimpan derita penduduk lokal. Breman menggambarkan tahap demi tahap terbentuknya “suatu sistem eksploitasi yang keras”. VOC dan kemudian pemerintah Hindia-Belanda tidak membangun perkebunan dengan tenaga kerja upahan bebas, melainkan memaksa rakyat Priangan menanam kopi sebagai kewajiban feodal. Rakyat desa harus menyediakan lahan dan tenaga tanpa upah memadai, di bawah pengawasan para penguasa lokal (Bupati dan Kepala Desa) yang menjadi kepanjangan tangan kolonial. Buku ini menjelaskan secara rinci kebijakan dan peraturan tanam paksa kopi: berapa batang pohon yang wajib ditanam tiap keluarga, bagaimana hasil panen harus disetor, hingga larangan bagi petani untuk meninggalkan desa atau beralih mata pencaharian. Semua aspek kehidupan diatur demi menjamin produksi kopi maksimal untuk ekspor.
Breman membagi bukunya ke dalam beberapa bab tematik dan kronologis. Bab awal menguraikan situasi Priangan sebagai frontier agrarian, daerah perintisan di pegunungan Jawa Barat yang penduduknya sedikit namun tanahnya subur. Selanjutnya, dibahas peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah kolonial (setelah VOC bangkrut tahun 1799), yang justru memperkuat sistem tanam paksa. Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811) muncul dalam narasi Breman sebagai tokoh yang mengatur ulang politik demografi Priangan. Ia mewajibkan para pemuda segera menikah dan melarang penduduk berpindah tempat, demi “memperbanyak tenaga kerja perkebunan”. Di era kultuurstelsel (Tanam Paksa, 1830 – 1870) di bawah Gubernur Jenderal van den Bosch dan penerusnya, sistem Priangan dijadikan model bagi seluruh Jawa. Breman menunjukkan bahwa meski fokus bukunya pada Priangan, praktik serupa meluas: desa-desa di Jawa dipaksa menanam komoditas ekspor seperti gula, nila, teh, selain kopi. Puncaknya, pada pertengahan abad ke-19, setengah kebutuhan kopi dunia disuplai dari Priangan.
Di bab-bab akhir, Breman mengungkap konsekuensi sosial ekonomi dari sistem kerja paksa ini. Populasi Priangan mengalami stagnasi pertumbuhan karena beban kerja berat dan kesehatan memburuk. Banyak petani kehilangan lahan pangan mereka. Lahan sawah digusur untuk kebun kopi. Kesengsaraan memicu perlawanan diam-diam. Para petani kerap melarikan diri ke daerah lain menghindari tanam paksa. Breman menggali arsip kolonial untuk mencatat insiden penduduk yang “hengkang” meninggalkan kampung demi menghindari kewajiban tanam kopi, misalnya eksodus sementara petani Cirebon pada 1809. Sistem ini baru mulai surut setelah 1870 dengan diberlakukannya Politik Liberal (yang mengizinkan perusahaan swasta), namun Breman mencatat bahwa kewajiban tanam kopi bagi petani Priangan ternyata bertahan hingga awal abad ke-20. Ringkasnya, isi utama buku ini adalah narasi mendalam tentang bagaimana Priangan dijadikan “lumbung kopi” dunia melalui kerja paksa, serta dampaknya yang melanggengkan kemiskinan struktural bagi kaum tani.
Argumen Utama Breman tentang Kerja Paksa Kolonial
Breman memiliki tesis sentral yang jelas yaitu kemakmuran kolonial Belanda dibangun di atas penderitaan dan kerja paksa kaum pribumi. Ia menentang keras narasi kolonial yang kerap mencoba “membenarkan” tanam paksa dengan dalih membawa kemajuan. Dalam buku ini, Breman membantah argumen kolonial bahwa “kerja paksa adalah jalan kemajuan”. Sebaliknya, data dan analisisnya menunjukkan bahwa sistem kerja paksa kopi mungkin mendongkrak perekonomian kolonial secara makro, tetapi sekaligus melumpuhkan ekonomi rakyat kecil. Ia menyimpulkan dengan tegas: “Pendapat bahwa ekonomi dan masyarakat kolonial dalam periode singkat ini telah berubah drastis adalah benar tetapi belumlah lengkap jika tidak sekaligus menyertakan pernyataan bahwa sistem tanam paksa sebagai sendi perubahan itu sudah sangat lama melumpuhkan kehidupan petani terutama di Kabupaten Priangan”. Artinya, ada kemakmuran semu di atas, tapi ada kehancuran perlahan di akar rumput.
Argumen utama Breman dapat dipahami melalui konsep kerja paksa yang didelegasikan. Pemerintah kolonial tidak menerapkan perbudakan langsung ala perkebunan Amerika, melainkan memakai struktur tradisional untuk memaksa rakyat. Bupati, Demang, dan Kepala Desa dijadikan perpanjangan tangan. Mereka diberi insentif berupa bagian keuntungan atau gaji, agar bersedia “memeras” rakyatnya sendiri bagi kepentingan kolonial. Strategi ini sebenarnya telah disadari oleh kritikus kolonial sejak zaman Multatuli. Breman membuka bukunya dengan mengutip pamflet Multatuli tahun 1862 yang menyindir taktik Belanda: “Jadi orang hanyalah perlu mendudukkan para Kepala mereka, dengan memberikan mereka sebagian dari keuntungan, … dan berhasillah semuanya dengan sempurna.”. Inilah kunci keberhasilan sistem Priangan: indirect rule (penguasaan tidak langsung) yang memanfaatkan elit lokal. Breman menegaskan bahwa tanpa kolaborasi para penguasa pribumi yang diikat kepentingan melalui pangkat dan komisi hasil panen. Tanam paksa mustahil berjalan lancar selama itu. Dengan kata lain, kolonialisme berhasil mencengkeram Priangan bukan melulu dengan senjata, tapi dengan kooptasi struktur feodal lokal.
Melalui arsip-arsip kolonial yang “diinterogasinya” secara kritis, Breman mengungkap detail bagaimana rakyat dipaksa bekerja. Tiap desa dibebani target tanam ribuan pohon kopi. Waktu dan tenaga petani tersedot untuk merawat tanaman kolonial di samping menggarap pangan sendiri (seringkali sawah terlantar). Hasil panen harus diantar ke gudang pemerintah. Breman menunjukkan betapa sepihak dan kejamnya sistem ini: “Mereka bukan saja dipaksa menanam kopi, tetapi juga mengantar hasil panennya ke gudang-gudang VOC dan menerima berapa pun harga yang ditentukan oleh VOC.” Petani tak punya daya tawar sama sekali. Harga ditetapkan sepihak serendah mungkin. Bahkan, menurut catatan sejarah yang dikutip Breman, ketika musim panen tiba “semua orang dikerahkan untuk memetik kopi – perempuan, anak-anak, bahkan orang tua renta sekalipun”. Tidak cukup sampai di situ, rakyat Priangan juga dipaksa melakukan kerja rodi lain seperti membangun jalan dan jembatan demi kelancaran angkutan kopi. Dengan gamblang Breman menyebut sistem ini sebagai bentuk perbudakan terselubung di tanah jajahan, di mana kebebasan dan kesejahteraan petani dikorbankan untuk keuntungan kolonial.
Argumen Breman juga mencakup adanya perlawanan dan kegigihan rakyat kecil menghadapi tekanan. Ia menyebut “kapasitas penduduk untuk resistensi dengan cara-cara ala Scottian” – merujuk pada James C. Scott. Yakni perlawanan tersembunyi seperti sabotase kecil, enggan bekerja, hingga migrasi keluar Priangan. Sistem tanam paksa tidak diterima begitu saja dengan pasrah. Banyak petani “melawan dengan kaki” meninggalkan desa atau bersembunyi dari kerja paksa. Meskipun perlawanan ini tidak terorganisir dalam pemberontakan besar, Breman berargumen bahwa akumulasi tindakan-tindakan kecil itu turut melemahkan efektivitas sistem pada jangka panjang. Singkatnya, argumen utama buku ini menyoroti ironi mendasar: demi keuntungan kolonial, Belanda menciptakan rezim kerja paksa yang berhasil secara ekonomi namun gagal secara kemanusiaan, dan justru menanam benih kemiskinan serta benih perlawanan di kalangan rakyat yang ditindasnya.
Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kolonial Hindia-Belanda
Dalam ulasannya, Breman secara tidak langsung melontarkan kritik tajam terhadap sistem ekonomi kolonial Belanda di Hindia Timur. Ia menggambarkan sistem tanam paksa kopi Priangan sebagai miniatur dari watak ekonomi kolonial secara keseluruhan. Eksploitatif, diskriminatif, dan berjangka panjang merusak tatanan lokal. Kritik Breman berangkat dari kenyataan bahwa kebijakan kolonial semata-mata berorientasi extractive, mengeruk sumber daya agraria dan tenaga kerja dengan imbalan minim. Pemerintah kolonial membanggakan peningkatan ekspor dan surplus anggaran yang diraih Cultuurstelsel, namun menutup mata bahwa surplus itu dihasilkan dengan “memindahkan kemiskinan” ke pundak petani Jawa. Breman menunjukkan bagaimana “para penguasa kaya, dan negeri Belanda siap melaksanakan proses modernisasinya” sementara rakyat yang menghasilkan surplus itu justru terpuruk miskin. Modernisasi Belanda pada abad ke-19 misalnya pembangunan perkeretaapian, industrialisasi sebagian besar dibiayai oleh de cultuurprocenten dan keuntungan tanam paksa, sesuatu yang jarang diakui secara moral oleh sejarah resmi Belanda.
Kritik Breman juga tertuju pada mitos-mitos kolonial yang membenarkan eksploitasi. Salah satunya adalah “pendapat etatis” bahwa tanam paksa membawa stabilitas dan pembangunan infrastruktur bagi pribumi. Para apologis kolonial berargumen, misalnya, bahwa jalan raya Anyer-Panarukan atau irigasi dibangun di era Cultuurstelsel sehingga petani juga kecipratan manfaat. Breman menyanggah halus anggapan ini. Ia mencatat bahwa proyek-proyek tersebut dibayar mahal dengan keringat dan nyawa pribumi (kerja rodi), dan manfaat jangka panjangnya pun lebih banyak dirasakan ekonomi kolonial daripada masyarakat lokal. Contohnya, pembangunan Jalan Raya Pos oleh Daendels memperlancar pengangkutan hasil bumi, tapi bagi rakyat itu berarti kewajiban kerja paksa baru yang tak kalah berat. Demikian pula, irigasi dan infrastruktur perkebunan dibuat terutama untuk kepentingan peningkatan produksi ekspor, bukan untuk ketahanan pangan petani. Kritik semacam ini sejalan dengan perspektif Breman yang memandang kebijakan kolonial secara keseluruhan tidaklah memajukan ekonomi lokal, melainkan merombak struktur agraria tradisional menjadi subordinat pasar global. Dalam proses perombakan itu, kelembagaan desa dihancurkan (misalnya melalui pelarangan sistem berhuma atau ladang berpindah), kemandirian petani hilang, dan tercipta ketergantungan penuh pada ekonomi uang yang dikendalikan kolonial.
Breman juga mengkritik praktik monopoli dan korupsi bawaan sistem kolonial. Sebagai contoh, ia menguraikan bagaimana VOC menetapkan standar berat kopi yang curang untuk menguntungkan pejabat: “sepikul kopi untuk pengapalan harus seberat 126 pon tapi untuk pembelian (dari petani) harus 140 pon”, selisih itu dalihnya untuk penurunan kadar air, tapi nyata-nyatanya “untuk keuntungan bagi pegawai”. Tambahan-tambahan beban semacam ini terus terjadi (pada 1777 dan 1797 takaran ditambah lagi tanpa alasan jelas) sehingga petani selalu dirugikan. Dengan membeberkan detail ini, Breman mengkritik moralitas ekonomi kolonial yang sarat penyalahgunaan kekuasaan. Bagi Breman, sistem ekonomi kolonial Hindia-Belanda bukan saja mengekspolitasi, tetapi juga secara sistematis menipu rakyat jajahan. Monopoli VOC (dan kelak pemerintah) melarang petani menjual kopi ke pedagang lain dengan harga wajar, sehingga petani terperangkap sebagai produsen dengan satu-satunya pembeli adalah pemerintah – suatu monopsoni total. Praktik seperti ini mengingatkan pada sistem ijer-ijeran (penyerahan hasil dengan harga ditentukan sepihak) yang jelas menindas. Breman menyebut secara tersirat bahwa penjajahan ekonomi seperti ini meniadakan mekanisme pasar bebas bagi pribumi; “pasar” hanya bebas bagi kaum kolonial, sementara penduduk lokal dipaksa ikut aturan sepihak.
Secara keseluruhan, kritik Breman terhadap ekonomi kolonial Belanda dapat dirangkum sebagai berikut: Belanda menerapkan kapitalisme semu di tanah jajahan keuntungan privat dimaksimalkan dengan biaya publik yang dipaksakan. Sistem tanam paksa kopi hanyalah salah satu contoh ekstrim di mana negara kolonial bertindak seperti korporasi besar yang mencari laba, mengubah petani menjadi semacam kuli yang dikurung di kampungnya sendiri. Tidak ada investasi balik yang berarti pada kesejahteraan rakyat; pendidikan hampir nihil, upah rendah, beban pajak tinggi, dan jika protes, aparat lokal maupun kolonial siap menindas. Breman dengan lantang mengingatkan bahwa sekalipun ekonomi kolonial Hindia-Belanda sempat tampak berjaya (dari sudut pandang Den Haag), fondasi kejayaan itu rapuh secara moral. Penderitaan manusia yang diakibatkan kelaparan, kemiskinan turun-temurun, ketidakadilan agraria meninggalkan “utang sejarah” yang besar. Kritik ini disampaikan Breman tidak dengan nada menggurui, melainkan dengan menghadirkan bukti-bukti konkret. Pembaca diajak menyaksikan ironi: bagaimana kopi yang harum di Eropa diseduh dari kepahitan hidup jutaan petani Priangan. Dengan demikian, Breman menelanjangi mitos pembangunan kolonial dan menegaskan sifat eksploitatif ekonomi kolonial Belanda di Indonesia.
Relevansi Temuan Breman terhadap Situasi Agraria dan Ketenagakerjaan Saat Ini
Membaca kisah tanam paksa kopi Priangan abad ke-18 dan 19 dalam buku Breman, tak pelak pikiran melayang ke kondisi agraria dan ketenagakerjaan Indonesia masa kini. Meskipun era kolonial telah berlalu 75 tahun lalu, gema dari sistem kerja paksa itu masih terasa dalam berbagai bentuk baru. Temuan-temuan Breman justru membuat kita merenung: sejauh mana pola eksploitasi kolonial itu meninggalkan warisan struktural yang terus memengaruhi petani dan buruh kita sekarang?
Pertama, dari sisi agraria, Breman menunjukkan bagaimana ketimpangan penguasaan lahan diciptakan dan dimanfaatkan oleh penguasa. Di Priangan kolonial, tanah-tanah subur secara efektif dimonopoli oleh negara (melalui kewajiban tanam komoditas tertentu) dan oleh elit (bupati mendapat cultuurgrond atau tanah lungguh untuk kopi). Petani kecil kehilangan kedaulatan atas tanahnya sendiri. Kini, situasi agraria Indonesia masih diwarnai ketimpangan mencolok. Sebagian besar lahan dikuasai segelintir tuan tanah, perusahaan besar (perkebunan, tambang, properti), sementara petani gurem banyak yang tak bertanah atau lahannya sempit. Pola “tanah hanya dikuasai segelintir orang” ini bahkan pernah diperingatkan Presiden Jokowi agar tidak terjadi lagi. Fakta di lapangan, konflik agraria masih marak. Masyarakat vs perusahaan perkebunan atau kehutanan mengindikasikan warisan sistem kolonial (monopoli lahan untuk komoditas ekspor) belum sepenuhnya hilang. Kasus perkebunan kelapa sawit misalnya, kerap melibatkan klaim negara atas tanah adat dan kemudian diberikan konsesi ke korporasi, membuat petani lokal tersingkir. Ini mengingatkan pada VOC mengambil alih Priangan dari Mataram lalu menjadikan penduduk setempat buruh di tanahnya sendiri.
Kedua, dari segi ketenagakerjaan, temuan Breman soal delegated labour coercion punya kemiripan dengan praktek masa kini, meski bentuknya lebih halus. Saat ini memang tidak ada kerja paksa resmi, tetapi kondisi kerja banyak buruh perkebunan dan pertanian masih jauh dari layak. Investigasi berbagai LSM mengungkap eksploitasi buruh perkebunan sawit, misalnya: upah sangat rendah, buruh diikat sistem target panen tinggi yang memaksa seluruh keluarga (termasuk istri dan anak) ikut bekerja tanpa upah tambahan. Ini mengingatkan kita pada cerita Breman tentang perempuan dan anak-anak Priangan dipaksa membantu panen tanpa bayaran. Selain itu, penggunaan tenaga kerja kontrak tidak tetap (buruh harian lepas) di perkebunan modern menjadikan posisi pekerja rentan, mirip ketidakpastian petani tanam paksa yang hidup dari sedikit lahan sisa dan upah borongan panen. Regulasi pemerintah seperti UU Cipta Kerja bahkan dinilai sebagian pengamat memperlemah perlindungan buruh dan memperkuat fleksibilitas yang rawan eksploitasi. Walau secara hukum sudah merdeka, hubungan kuasa antara pemilik modal/otoritas dengan pekerja kecil masih timpang. Pola “ambil untung maksimal dengan biaya tenaga kerja minimal” yang diulas Breman soal VOC bisa dilihat analoginya dalam praktik upah murah atau outsourcing masa kini.
Ketiga, Breman menyoroti peran elit lokal dalam eksploitasi kolonial. Saat ini, kita pun melihat gejala di mana segelintir elit (baik itu oknum pejabat daerah, tokoh adat yang co-opted, atau pengusaha lokal) berkolaborasi dengan investor besar dalam proyek yang kadang merugikan rakyat kecil. Misalnya, ada kasus-kasus kepala daerah memberikan izin lahan yang mengabaikan hak masyarakat, demi investasi perkebunan atau tambang. Ini bukan kerja paksa ala kolonial, tetapi polanya serupa. Ada persekutuan kepentingan antara kekuasaan dan modal yang potensi mengorbankan rakyat biasa. Bupati Priangan dahulu diberi persen keuntungan agar memaksa rakyat menanam kopi, kini mungkin dalam bentuk bagi hasil saham atau kompensasi proyek.
Keempat, soal kemiskinan agraria. Breman menjelaskan asal-usul kemiskinan kronis rakyat Priangan sebagai akibat langsung drainase kolonial kekayaan disedot ke luar, yang tertinggal hanya subsistensi minimum. Pasca kemerdekaan, apakah pola ini berubah? Memang secara ekonomi nasional, kekayaan tidak lagi mengalir ke Belanda. Namun dalam era globalisasi, mekanisme yang mirip drainage kadang terjadi. Misalnya keuntungan dari komoditas (kelapa sawit, karet, kopi juga) lebih banyak dinikmati rantai perdagangan global dan segelintir eksportir, sementara petani produsen mendapat harga rendah. Ketika Breman menulis “kopi memang pahit buat rakyat Priangan”, itu bisa bergema menjadi “sawit itu pahit bagi buruh dan petani lokal” jika melihat kondisi buruh sawit sekarang yang hidup pas-pasan meski industri sawit meraup devisa besar. Artinya, struktur ekonomi yang timpang yang dibentuk sejak era kolonial masih perlu dirombak untuk benar-benar memakmurkan produsen di level bawah.
Selain itu, kehilangan hak dan keterkungkungan yang dialami petani Priangan dulu memiliki relevansi pada isu migrasi dan urbanisasi sekarang. Breman mencatat penduduk Priangan dikurung di desa, dilarang pindah, semata agar menjadi tenaga kerja tetap. Pasca kolonial, memang orang bebas pindah, tapi karena desa-desa tetap miskin, kita menyaksikan eksodus besar-besaran pemuda desa menjadi buruh kota atau TKI ke luar negeri. Ini kebalikan situasi dulu, tapi akarnya sama. Desa agraris tidak memberikan kehidupan layak akibat struktur agraria timpang. Jadi warisan itu muncul dalam bentuk arus tenaga kerja keluar dari sektor pertanian. Masalah ketimpangan desa-kota, Jawa-luar Jawa, sedikit banyak berakar dari sejarah kebijakan kolonial yang memfokuskan pembangunan ekonomi pada kantong-kantong perkebunan dan kota pelabuhan saja. Breman mengajak kita memahami bahwa sejarah sangat mempengaruhi wajah masyarakat kini.
Yang tidak kalah penting, temuan Breman relevan secara politis dalam hal keadilan sejarah. Wacana tentang pengakuan atau bahkan tuntutan ganti rugi atas kerja paksa zaman kolonial kadang mencuat. Buku Breman memperkuat posisi bahwa memang ada keuntungan kolonial yang diperoleh dengan cara tidak adil. Diskursus ini bisa memantik kesadaran generasi kini untuk tidak melupakan sejarah penindasan, sekaligus mendorong sikap kritis terhadap bentuk-bentuk penjajahan gaya baru. Kolonialisme modern bisa berwujud korporatokrasi global, misalnya penguasaan sumber daya oleh perusahaan multinasional tanpa memperhatikan hak-hak komunitas lokal. Kasus pembakaran hutan untuk kebun adalah alarm bahwa mentalitas kolonial (“ambil untung, tak peduli kerusakan dan penderitaan orang kecil”) masih hidup.
Sebagai penutup, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa bukan hanya buku sejarah, melainkan cermin bagi Indonesia kontemporer. Breman berhasil menyuguhkan pelajaran berharga: bahwa ketidakadilan agraria dan eksploitasi tenaga kerja bukan fenomena baru, melainkan telah berakar lama. Tantangannya bagi kita adalah memutus rantai ketidakadilan itu. Selama petani dan buruh masih terpinggirkan, selama model pembangunan masih mengorbankan “orang kecil” demi pertumbuhan, maka bayang-bayang tanam paksa masih menyertai perjalanan bangsa ini. Buku Jan Breman mengingatkan kita untuk terus memperjuangkan agar kemakmuran tidak lagi dibangun di atas penderitaan sebagian rakyat. Sejarah pahit itu harus menjadi penggerak perubahan, karena seperti dikatakan Breman sendiri, memahami masa lalu memberi kita kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih adil. Semoga “pahitnya kopi” di masa lalu bisa menjadi pelajaran agar manisnya kemerdekaan bisa benar-benar dirasakan hingga lapisan terbawah masyarakat Indonesia.
Sumber:
- Breman, Jan. Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720–1870. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
