Resensator: Bdikar Anumtiko Ling Kricas
Latar Belakang dan Pokok Persoalan
Buku “Agriculture and the Generation Problem” karya Ben White adalah sebuah refleksi mendalam tentang persoalan regenerasi dalam sektor pertanian, khususnya di negara-negara Selatan. White menyebut fenomena ini sebagai “generation problem” dalam pertanian—masalah struktural yang menyebabkan semakin sedikitnya generasi muda yang tertarik atau mampu bertahan di sektor pertanian kecil dan tradisional. Isu ini bukanlah sesuatu yang lahir dari kemalasan atau ketidaktertarikan kaum muda semata, melainkan akibat dari sistem ekonomi-politik yang menyulitkan mereka untuk mengambil alih peran generasi sebelumnya.
White menegaskan bahwa kaum muda tidak secara sukarela meninggalkan pertanian, melainkan didorong keluar oleh struktur-struktur yang membuat pertanian berskala kecil menjadi tidak layak. Ini mencakup perampasan tanah, ketimpangan akses terhadap modal, hingga kebijakan pembangunan yang bias terhadap industrialisasi dan pertanian skala besar. Dalam pandangan White, ketidakmampuan generasi muda untuk mengakses tanah adalah salah satu bentuk kegagalan negara dalam menyusun kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan.
White mengaitkan fenomena ini dengan dinamika globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Di banyak negara, tanah pertanian semakin terkonsolidasi ke tangan segelintir elite atau korporasi agrobisnis dan diperparah oleh masuknya investasi asing yang berorientasi ekspor, menyebabkan penggusuran petani kecil dan mempersulit anak-anak muda desa untuk mewarisi tanah keluarga mereka. Model pembangunan semacam ini justru menciptakan ketergantungan baru terhadap upah buruh migran dan memperparah urbanisasi paksa.
Kritik utama White terletak pada bagaimana negara dan lembaga internasional seringkali meluncurkan kebijakan pemuda pertanian tanpa melihat akar struktural dari krisis regenerasi ini. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan teknologi, atau akses kredit tidak akan menyelesaikan masalah jika tanah tetap tidak tersedia dan tidak terjangkau oleh generasi muda. Karena itu, White menekankan bahwa kebijakan regenerasi pertanian harus dimulai dari kebijakan tanah.
Buku bagus ini juga mengangkat pentingnya memahami pertanian sebagai ruang reproduksi sosial. Di banyak komunitas, pertanian bukan sekadar soal produksi pangan, tetapi juga tempat berlangsungnya pewarisan budaya, pengetahuan ekologis, dan hubungan sosial antargenerasi. Ketika generasi muda terusir dari tanah, yang hilang bukan hanya petani masa depan, tetapi juga jembatan antara masa lalu dan masa depan masyarakat desa.
White meneliti beragam kasus dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk menunjukkan bahwa masalah ini bersifat global namun memiliki konteks lokal yang unik. Di Indonesia, misalnya, konflik agraria yang berlangsung terus-menerus, alih fungsi lahan untuk industri, dan minimnya keberpihakan kebijakan kepada petani kecil menjadi faktor penghambat regenerasi petani. Meskipun banyak pemuda desa masih memiliki ikatan emosional dengan tanah leluhur, realitas ekonomi membuat mereka enggan untuk bertani.
Salah satu kontribusi penting dari buku ini adalah dekontruksi terhadap narasi pembangunan yang menyederhanakan masalah regenerasi menjadi soal minat atau pendidikan. White mengingatkan bahwa minat generasi muda tidak dapat tumbuh jika tidak ada jaminan hak, pengakuan atas kedaulatan tanah, dan kepastian masa depan. Regenerasi pertanian bukan soal mentalitas, tetapi soal struktur dan keadilan.
Lebih jauh, White menawarkan perspektif interseksional yang menghubungkan kelas, generasi, dan gender. Ia menunjukkan bahwa perempuan muda di pedesaan menghadapi hambatan ganda: mereka tidak hanya kesulitan mengakses tanah, tetapi juga dibatasi oleh norma gender patriarkal dalam keluarga dan masyarakat. Maka, regenerasi petani juga mensyaratkan transformasi gender yang mendalam.White juga mengangkat berbagai bentuk perlawanan dan inovasi yang dilakukan oleh generasi muda. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, ada kelompok petani muda yang membentuk kolektif pertanian, mengembangkan praktik agroekologi, dan menggunakan media sosial untuk membangun jaringan solidaritas. Ini menunjukkan bahwa generasi muda bukan hanya korban, tetapi juga aktor perubahan.
Dalam konteks Indonesia, buku ini memberikan refleksi tajam terhadap kegagalan program-program pemerintah seperti food estate atau redistribusi tanah yang tidak menyentuh akar persoalan. Tanpa reformasi agraria yang sejati dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat serta petani muda, upaya regenerasi hanya akan menjadi slogan kosong. Kekuatan buku ini terletak pada kombinasi antara riset empiris yang kuat, refleksi teoretik yang mendalam, dan kepekaan politik yang tajam. White bukan hanya menganalisis struktur, tetapi juga membuka ruang bagi suara-suara petani muda yang sering diabaikan dalam diskursus pembangunan. Ia menulis dengan kepedulian dan semangat keadilan agraria.
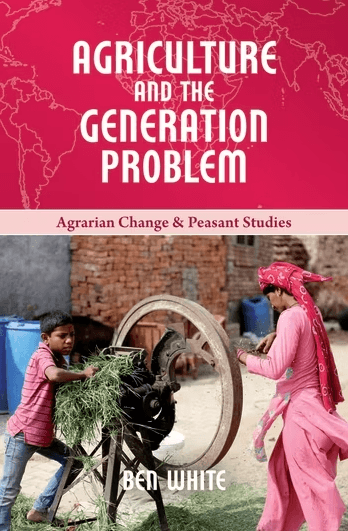 Argumen Utama: Politik Tanah, Kebijakan, dan Ketimpangan Intergenerasional
Argumen Utama: Politik Tanah, Kebijakan, dan Ketimpangan Intergenerasional
Krisis regenerasi petani bukanlah persoalan individual atau sektoral semata, melainkan merupakan akibat langsung dari struktur agraria global yang timpang. Ben White dalam bukunya Agriculture and the Generation Problem menyoroti bahwa kegagalan sistem pertanian dalam menarik generasi muda bukan disebabkan oleh hilangnya minat semata, tetapi lebih karena terdesaknya ruang hidup dan peluang struktural bagi kaum muda di pedesaan. Dalam pandangan White, kaum muda sering kali menghadapi hambatan ganda: dari dalam keluarga petani sendiri yang mengalami tekanan ekonomi, hingga struktur kebijakan nasional dan internasional yang tidak berpihak pada pertanian rakyat.
White menjelaskan bahwa dalam sistem pertanian keluarga, alih generasi dalam penguasaan lahan tidak selalu berjalan mulus. Sistem warisan sering kali menyebabkan lahan terfragmentasi, atau malah dikuasai oleh anggota keluarga yang lebih kuat secara ekonomi. Di sisi lain, kaum muda yang ingin bertani mandiri kesulitan mengakses lahan karena harga tanah yang melonjak atau sudah dikuasai oleh korporasi besar. Proses konsolidasi tanah secara sistemik, baik oleh negara maupun swasta, membuat ruang agraria semakin sempit bagi generasi muda. Dalam konteks ini, White menyatakan bahwa liberalisasi ekonomi berperan besar dalam mempersempit akses ini.
Salah satu kutipan penting White adalah bahwa, “a meaningful rural youth policy must be land policy, agrarian policy, and employment policy rolled into one.” Ini menunjukkan bahwa solusi regenerasi tidak bisa disederhanakan menjadi pelatihan kewirausahaan atau pemberdayaan teknis semata. Tanpa adanya reformasi struktural dalam kebijakan pertanahan, perburuhan pedesaan, dan distribusi sumber daya, maka program-program tersebut hanya akan menyentuh permukaan masalah. White menyerukan perlunya pendekatan holistik yang menempatkan kaum muda sebagai aktor utama dalam sistem pangan dan agraria, bukan sekadar penerima pelatihan atau tenaga kerja murah.
Lebih lanjut, White juga membongkar mitos narasi pembangunan yang menjadikan kaum muda sebagai simbol “modernisasi”. Dalam proyek-proyek pembangunan internasional, anak muda kerap digambarkan sebagai kelompok yang harus “diangkat” dari pertanian menuju pekerjaan formal di kota. Padahal, bagi banyak kaum muda, bertani tetap menjadi pilihan strategis jika didukung oleh kondisi yang adil dan menguntungkan. Di sinilah, menurut White, muncul paradoks: pembangunan justru mendorong urbanisasi paksa dan meninggalkan potensi regeneratif di sektor pertanian.
White juga menekankan bahwa pertanian bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan ruang sosial-politik tempat identitas, hubungan antar generasi, dan kedaulatan lokal dibangun. Ketika tanah dan produksi pangan dikontrol oleh korporasi atau program negara yang tidak akuntabel, maka kaum muda kehilangan bukan hanya penghidupan, tetapi juga otonomi. Dalam beberapa studi kasus yang diangkat, White memperlihatkan bagaimana kelompok muda di berbagai negara mencoba melawan dominasi ini melalui koperasi, gerakan agroekologi, atau inisiatif reforma agraria lokal.
Dalam konteks Indonesia, pemikiran White sangat relevan. Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah kerap berorientasi administratif (melalui sertifikasi), tanpa benar-benar membuka akses struktural terhadap tanah bagi generasi muda. Petani muda di berbagai wilayah mengalami kesulitan mengakses lahan karena dominasi HGU, korporasi perkebunan, atau bahkan program food estate. Maka, regenerasi petani harus dipahami sebagai agenda politik, bukan sekadar demografi atau teknokrasi pertanian.
Apa yang ditawarkan White bukanlah resep instan, melainkan kerangka berpikir ulang tentang struktur agraria. Ia mengajak kita untuk melihat kaum muda bukan sebagai beban, tetapi sebagai aktor perubahan dalam perjuangan agraria. Untuk itu, perlu aliansi luas antara organisasi petani, gerakan pemuda, akademisi kritis, dan pembuat kebijakan yang berpihak. Tanpa keberpihakan politik, regenerasi petani hanya akan menjadi slogan kosong di tengah krisis pangan dan iklim yang semakin mengancam.
Akhirnya, Agriculture and the Generation Problem adalah sebuah seruan intelektual dan moral untuk merebut kembali ruang agraria yang semakin dikuasai oleh logika kapital. White menempatkan regenerasi petani dalam kerangka keadilan sosial dan kedaulatan pangan, menantang kita untuk melampaui pendekatan teknokratis yang mendepolitisasi masalah. Buku ini penting dibaca oleh siapa pun yang peduli terhadap masa depan pertanian dan kehidupan pedesaan yang berkelanjutan.
Relevansi dan Kritik: Tantangan dan Implikasi di Indonesia
Pemikiran Ben White dalam Agriculture and the Generation Problem menggema kuat di konteks Indonesia, negara dengan sejarah panjang ketimpangan agraria dan keterbatasan akses lahan bagi generasi petani muda. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai program pembangunan seperti food estate dan transmigrasi, alih-alih membuka akses terhadap sumber daya agraria, justru memperparah ketimpangan struktural yang telah lama mengakar. Proyek-proyek tersebut seringkali mengabaikan relasi historis dan kultural masyarakat lokal terhadap tanah, serta mempersempit ruang hidup dan usaha tani bagi generasi muda pedesaan. Dengan kata lain, pemuda tidak meninggalkan pertanian karena kemalasan, melainkan karena dipinggirkan oleh kebijakan pembangunan itu sendiri.
White secara tajam membongkar mitos-mitos dominan dalam narasi pembangunan pertanian. Salah satu mitos yang dikritiknya adalah pandangan bahwa generasi muda “tidak tertarik” pada pertanian. Ia mengajak kita melihat bahwa pilihan untuk keluar dari pertanian sering bukan didorong oleh keinginan, melainkan karena struktur yang tidak mendukung: harga tanah yang melambung, akses terhadap kredit yang sulit, dan rendahnya dukungan kebijakan yang melindungi usaha tani kecil. Dalam konteks Indonesia, mitos ini diperkuat oleh stigma sosial bahwa bertani adalah pekerjaan rendah dan tidak menjanjikan masa depan, padahal justru karena absennya dukungan sistemik, bukan karena karakter individu pemuda.
Kritik White menjadi relevan ketika kita mengamati bahwa program-program pemerintah seperti reforma agraria seringkali bersifat simbolik atau administratif, misalnya sekadar pembagian sertifikat tanah tanpa memperbaiki kondisi riil bagi regenerasi petani. Apalagi dalam konteks food estate, banyak wilayah adat dan pertanian lokal diambil alih untuk dijadikan proyek besar berbasis korporasi. Dalam banyak kasus, anak-anak petani tidak lagi memiliki lahan yang bisa diwariskan karena telah dikonsesikan kepada perusahaan besar, menjadikan regenerasi pertanian sebagai ilusi belaka. Dalam kondisi semacam ini, kebijakan negara justru mempersempit regenerasi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria.
Salah satu kekurangan dalam analisis White adalah kurangnya eksplorasi terhadap berbagai bentuk inovasi dan perlawanan yang sebenarnya telah dikembangkan oleh generasi muda di banyak tempat. Di berbagai wilayah Indonesia, kita bisa melihat munculnya gerakan pertanian alternatif berbasis komunitas, praktik agroekologi, koperasi petani muda, hingga proyek digitalisasi pasar hasil pertanian. Misalnya, gerakan seperti Petani Muda Keren di Jawa atau Sekolah Tani Agroekologi di Sumatera telah membuktikan bahwa pemuda tidak kekurangan semangat atau kreativitas, tetapi sistem agraria dan ekonomi yang mengekang ruang gerak mereka.
Sayangnya, dinamika perlawanan ini belum mendapatkan tempat yang memadai dalam kajian White. Sementara buku ini sangat kuat dalam menganalisis dimensi struktural dan global dari krisis regenerasi, ia belum cukup memberi ruang untuk narasi alternatif yang muncul dari bawah. Padahal, bentuk-bentuk perlawanan ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa regenerasi petani bukan hanya mungkin, tetapi sedang terjadi—meskipun seringkali tanpa dukungan negara. Dalam konteks inilah, penting untuk melengkapi kajian White dengan penelitian-penelitian lapangan yang menyoroti pengalaman dan strategi anak muda petani dalam bertahan dan berinovasi.
Lebih dari sekadar kajian akademik, karya White merupakan ajakan politis untuk merekonstruksi cara pandang kita terhadap pertanian dan pemuda. Ia menolak pendekatan teknokratis dan mengajak untuk membingkai ulang regenerasi petani sebagai bagian dari keadilan intergenerasional. Ini berarti tidak hanya memberikan akses lahan kepada anak muda, tetapi juga merombak sistem ekonomi yang menempatkan pertanian di posisi marjinal dalam agenda pembangunan. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan pangan, di mana hak untuk bertani, mengakses tanah, dan menentukan sistem produksi pangan berada di tangan rakyat itu sendiri.
Dalam konteks ASEAN dan Global South secara umum, buku ini juga menjadi refleksi atas warisan kolonialisme dalam kebijakan pertanian dan agraria. Negara-negara berkembang yang pernah dijajah sering kali mewarisi sistem pertanahan yang eksploitatif dan elitis. Ketika liberalisasi ekonomi masuk, sistem ini tidak dibongkar, tetapi justru diperkuat oleh investasi skala besar dan pasar global yang tidak adil. White melihat dengan jeli bagaimana rezim ekonomi global menciptakan generasi muda yang tercerabut dari akar agrarianya, namun kemudian dituduh sebagai tidak produktif atau malas. Narasi ini perlu dibalik melalui perspektif struktural dan keadilan historis.
Kesimpulannya, Agriculture and the Generation Problem adalah karya penting untuk memahami relasi antara generasi muda dan krisis pertanian di era neoliberal. White berhasil mengungkap bahwa regenerasi petani tidak mungkin tercapai tanpa perubahan radikal dalam kebijakan tanah, akses terhadap sumber daya, dan penghargaan terhadap kehidupan desa. Buku ini bisa menjadi bahan bakar intelektual dan advokasi untuk mendorong kebijakan agraria yang berpihak pada generasi muda. Namun, ia juga perlu dilengkapi dengan narasi harapan dan perjuangan dari bawah agar menjadi lebih utuh dan transformatif.
Tugas kita bukan hanya membaca buku ini, tetapi juga meradikalisasi pesannya dalam kerja-kerja advokasi dan gerakan sosial. Kita perlu menegaskan bahwa masa depan pertanian tidak hanya bergantung pada “kemauan” pemuda, tetapi pada keberanian kolektif untuk mengubah sistem agraria yang tidak adil. Regenerasi petani adalah perjuangan melawan pelupaan sejarah dan pembajakan masa depan.
