Resensator: Erwin Basrin
Properti bukanlah konsep hukum yang kaku; melainkan sebuah institusi sosial yang fleksibel dan dinamis, dibentuk oleh relasi-relasi sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Buku Property in Social Continuity menelaah hal ini melalui studi kasus masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Franz von Benda-Beckmann (1979) menyoroti bahwa warisan harta dan jabatan merupakan “kendaraan kesinambungan” sosial yang menjaga kelangsungan kelompok berdasarkan kekerabatan dan keturunan. Dengan fokus pada hukum waris Minangkabau dan interaksinya dengan nilai Islam dan hukum Barat, penulis menggambarkan bagaimana sistem kepemilikan tanah dan warisan di Minangkabau berkembang tanpa kehilangan jati diri sosialnya.
Keistimewaan pendekatan ini adalah menempatkan hubungan kepemilikan dalam konteks pluralisme hukum: hukum adat matrilineal, hukum negara, dan norma keagamaan yang saling beriringan. Gagasan utama Benda-Beckmann adalah bahwa properti harus dianalisis lewat tiga elemen utama yaitu pemegang hak (individu maupun kelompok sosial), objek properti, dan hak/kewajiban yang melekat pada pemegang tersebut. Konsep “bundle of rights” atau himpunan hak menjadi kunci: berbagai pihak bisa memiliki hak yang berbeda-beda atas satu objek. Misalnya, hak regulasi dan pengendalian bisa dipegang oleh lembaga adat secara komunal, sementara hak guna dan pewarisan dialokasikan kepada individu dalam keluarga.
 Kerangka bundle of rights: Benda-Beckmann menggambarkan properti sebagai himpunan hak dan kewajiban yang dapat dialokasikan secara berlapis. Berbagai pemegang (keluarga, marga, individu) bisa memegang hak berbeda atas satu tanah. Pemisahan antara hak representasi eksternal (misalnya kepala marga mengendalikan tanah adat) dengan hak penggunaan internal (anggota keluarga memanen hasil tanah) sangat penting.
Kerangka bundle of rights: Benda-Beckmann menggambarkan properti sebagai himpunan hak dan kewajiban yang dapat dialokasikan secara berlapis. Berbagai pemegang (keluarga, marga, individu) bisa memegang hak berbeda atas satu tanah. Pemisahan antara hak representasi eksternal (misalnya kepala marga mengendalikan tanah adat) dengan hak penggunaan internal (anggota keluarga memanen hasil tanah) sangat penting.- Lapisan sosial properti: Ia menekankan tiga lapisan sosial kepemilikan – ideal budaya (ideologi adat), institusi hukum (norma tertulis atau tidak tertulis), dan praktik sosial di lapangan. Meskipun tiap lapisan itu saling terkait, memahami mereka secara terpisah membantu menjelaskan perbedaan konsep kepemilikan antara adat dan hukum negara.
- Embeddedness dan kesinambungan: Studi kasuistik dalam buku ini menunjukkan bahwa hubungan properti sangat “tertambat” dalam struktur sosial. Perubahan ideologi atau kebijakan hukum tidak selalu langsung merombak relasi properti yang sudah kuat. Sebagai contoh, ada resistensi terhadap perubahan radikal: meski rezim kolonial atau negara mengubah aturan, hak milik adat Minangkabau cenderung terus dijaga melalui praktik kekerabatan. Property terus berfungsi untuk menjaga kesinambungan sosial masyarakat matrilineal itu.
Pendekatan Benda-Beckmann juga membawa wawasan baru bagi studi hukum dan antropologi. Ia mendorong peneliti untuk menghindari kategori Barat yang baku (“Negara”, “Komunal”, “Privat”), karena realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Misalnya, beliau menunjukkan bahwa istilah “komunal” kerap disalahpahami. Dalam kasus Minangkabau, kepemilikan pusaka adat yang tampak komunal sebenarnya melibatkan pembagian hak internal yang rumit. Dengan cara ini, kerangka analitisnya membuka cara pandang baru, hak milik dianggap sebagai rangkaian relasi sosial dan proses yang berlapis, bukan objek tunggal. Pendekatan empiriknya berlandaskan riset lapangan jangka panjang dan data sejarah memberikan kerangka lintasbudaya yang kaya. Seperti disimpulkan oleh Baerends dalam ulasannya, pendekatan ini menekankan agar peneliti “menyumbangkan pengalaman sendiri” ketimbang memaksakan data ke kategori ideologis Barat yang sudah jadi.
Konsep-konsep Benda-Beckmann sangat relevan dalam konteks hukum adat, konflik agraria, dan keberlanjutan sosial di Indonesia. Di Indonesia berlaku pluralisme hukum, hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan. Namun perbedaan mendasar sering kali memicu gesekan. Sebagai contoh, hukum adat menekankan nilai kolektifitas dan keadilan substantif di dalam komunitas, sedangkan hukum negara bersifat universal dan prosedural. Ketidakselarasan ini mengakibatkan sengketa lahan kerap timbul. Para ahli mencatat betapa pengakuan terhadap hak adat selama ini sering terjadi “secara ambigu dan berada di bawah kendali negara”, yang mengakibatkan kebingungan dalam penegakan hukum dan konflik agraria.
Relasi properti fleksibel Benda-Beckmann membantu menjelaskan mengapa konflik semacam itu kompleks. Sebuah petak tanah bisa saja memiliki hak ulayat adat kolektif, hak milik individu, dan status hukum negara sekaligus. Pendekatan bundle of rights mengilustrasikan bagaimana hak-hak tersebut dapat bersinggungan dan berubah menurut kepentingan pihak yang berkuasa. Misalnya di Minangkabau, tanah pusaka adat (tanah ulayat) dikelola oleh nagari secara kolektif, tetapi pemanfaatannya diberikan kepada anggota matrilineal tertentu. Pemahaman seperti ini penting untuk merumuskan kebijakan agrarian yang memahami bahwa hak atas tanah bukan monolitik memudahkan penyusunan solusi adil dan berkelanjutan.
Demikian pula, ide-ekologis dan keberlanjutan sosial di Indonesia mendapat manfaat dari kerangka ini. Dengan mengakui peran kolektif masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya, negara dapat mendorong manajemen lingkungan berkelanjutan. Bukti empiris Benda-Beckmann setara ajarannya, kajian-kajian tindak lanjut menunjukkan bahwa pengakuan hak adat bisa mencegah eksploitasi berlebihan, tetapi hanya jika pluralisme hak diakui secara nyata. Para pembuat kebijakan kini menyadari bahwa hak milik membawa kewajiban sosial dan lingkungan; konsep “bundle” memperlihatkan betapa setiap aktor hanya memegang sebagian hak pakai dari keseluruhan. Hal ini sangat relevan dalam proyek pembangunan berkelanjutan, hanya dengan memetakan relasi hak yang beragam barulah usaha konservasi lahan atau hutan dapat berjalan efektif, tanpa menimbulkan konflik baru.
Secara kritis, pendekatan teoritis Benda-Beckmann menjadi jembatan antara disiplin hukum dan antropologi. Dengan cara analisis lintas budaya yang kaya data, ia menantang asumsi dogmatis tentang kepemilikan. Karya ini memperkaya teori legal pluralism yakni properti tidak lagi dipandang semata-mata sebagai produk negara atau pasar, melainkan sebagai fenomena sosial-historis. Selain konsep bundle of rights, ia mengangkat konsep “force fields” (kekuatan politik-ekonomi) yang menggerakkan dinamika hak milik. Kontribusi penting lainnya adalah menunjukkan bahwa ideologi Barat tentang hak milik (misal, privasi individu, penuntasan hutan rakyat secara kolektif, dll.) sering tak berlaku di banyak masyarakat. Sebagai contoh, ia menulis bahwa asumsi lama seperti kepemilikan negara mutlak terbantahkan oleh bukti sejarah, hak milik sering ada bahkan sebelum negara terbentuk. Sehingga, studinya membuka pandangan baru yang menempatkan masyarakat plural sebagai subjek aktif dalam pembentukan norma hukum, bukan hanya objek kebijakan.
Dalam kesimpulan, Property in Social Continuity menegaskan bahwa properti adalah jiwa sosial, perubahan hukumnya harus dilihat dalam kerangka sosial kultural yang dinamis. Benda-Beckmann berhasil menautkan teori dan empirika untuk menantang kategori baku dan menekankan kesinambungan adat dalam masyarakat plural. Pendekatannya tidak hanya relevan bagi studi Minangkabau, tetapi juga memandu refleksi keilmuan mengenai konflik agraria dan perwujudan hak milik yang beragam di Indonesia. Seperti disarankan oleh pengulasnya, kerangka analitis ini sangat berguna bagi peneliti hukum dan antropologi yang ingin mengembangkan teori hak milik berbasis pengalaman empiris. Bagi pembaca di bidang hukum, antropologi, dan agraria, buku ini membuka cara pandang baru untuk memahami hak milik sebagai rangkaian relasi sosial yang terus bergerak, bukan sekadar dokumen kepemilikan kaku. Referensi analitis Benda-Beckmann memberikan alat konseptual penting untuk merancang kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan di negeri berpluritas hukum seperti Indonesia.
Referensi: Temuan dan konsep dalam esai ini dirujuk dari literatur akademik terkini dan klasik mengenai properti dan pluralisme hukum, termasuk analisis terhadap Property in Social Continuity (von Benda-Beckmann 1979/2000).

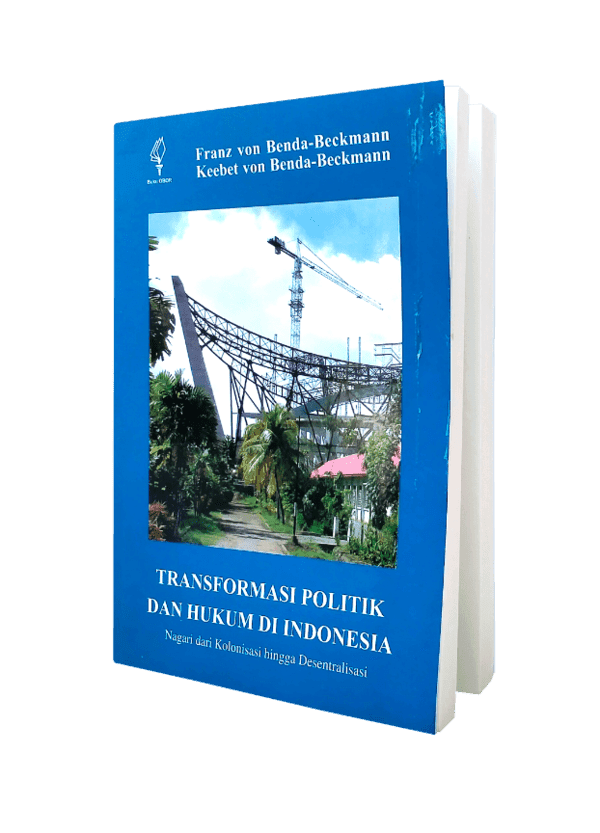 Kerangka bundle of rights: Benda-Beckmann menggambarkan properti sebagai himpunan hak dan kewajiban yang dapat dialokasikan secara berlapis. Berbagai pemegang (keluarga, marga, individu) bisa memegang hak berbeda atas satu tanah. Pemisahan antara hak representasi eksternal (misalnya kepala marga mengendalikan tanah adat) dengan hak penggunaan internal (anggota keluarga memanen hasil tanah) sangat penting.
Kerangka bundle of rights: Benda-Beckmann menggambarkan properti sebagai himpunan hak dan kewajiban yang dapat dialokasikan secara berlapis. Berbagai pemegang (keluarga, marga, individu) bisa memegang hak berbeda atas satu tanah. Pemisahan antara hak representasi eksternal (misalnya kepala marga mengendalikan tanah adat) dengan hak penggunaan internal (anggota keluarga memanen hasil tanah) sangat penting.